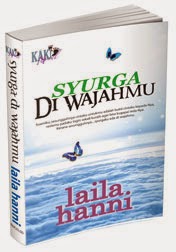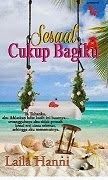Bab 26
Sarah berlari ke sana dan ke mari di taman permainan itu. Lepas satu, satu permainan yang ada di situ itu dinaikinya. Gelongsor, buaian kecil, kuda mainan dan juga jongkang jungkit, semuanya ingin dicubanya. Gembira sekali dia dalam dunianya. Ketawa sendirian apabila ada yang menggeletek hatinya. Pengasuhnya juga pandai sekali melayan kerenahnya. Sabar sekali dia menuruti tubuh kecil itu berpindah dari satu permainan ke permainan yang lain.
Mataku terus-terusan menetap tubuh kecil itu. Ah ... sungguh aku rindu padanya. Dua minggu aku tidak dapat kemari. Dua minggu lepas aku terpaksa bekerja walaupun di hari minggu kerana memantau proses peperiksaan bagi pelajar Program Pengajian Jarak Jauh. Minggu berikutnya pula aku ke rumah ibu-bapa Suzana di Melaka untuk menghadiri majlis perkahwinannya. Meriah sekali majlis tersebut. Aku yang berada di sana selama dua hari dikejutkan dengan kehadiran jiranku, Umar Rafiki.
Terasa bagaikan di awang-awangan apabila melihatkan dia melangkah menghampiri aku ketika menyaksikan Suzana dan Haziq yang sedang bersanding di atas pelamin. Entah mengapa, tiba-tiba terlintas di hatiku bahawa satu hari nanti aku juga akan berada di situ. Dan dia akan berada di sampingku. Ah Munirah ... mengapa pula ke situ fikiranmu? Bodohnya kamu memasang angan-angan sebegitu. Tidak... tidak mungkin itu akan jadi kenyataan. Tidak sedarkah engkau akan siapa dirimu.
Cepet-cepat aku memejamkan mataku, cuba membuang jauh semua angan-angan gila itu. Aku sedikit pun tidak layak untuk mengangan-angankan perkara itu. Aku harus menumpukan kembali perhatianku pada Sarah. Segala-galanya tentang Sarah amat membahagiakan hati ini. Sudah terlalu lama rasanya aku hanya memandang dari jauh tubuh kecil itu. Sudah terlalu lama rasanya aku menanti dengan sabar saat-saat aku berani untuk menghampirinya. Hari ini aku nekad, aku akan mendekatinya. Aku ingin mendengar suaranya. Tempoh tiga bulan hanya memandang dari jauh akan aku akhiri hari ini.
Perlahan-lahan aku menarik nafas dan memulakan langkah menghampirinya. Aku tahu aku perlu berhati-hati supaya pengasuhnya tidak akan mensyaki apa-apa. Sarah sedang menunggang sebuah kuda permainan yang dipasang pada sebuah spring besar. Terbua-buai tubuh kecil itu apabila dia menghayunkan tubuhnya ke hadapan dan ke belakang mengikut hayunan spring tersebut. Wajahnya yang ceria menggambarkan keseronokkan yang dirasakannya.
Pengasuhnya kini sedang duduk berbual bersama dengan seorang pengunjung yang turut sama membawa anaknya ke sini. Kepenatan agaknya ke sana sini malayan Sarah dari tadi. Sesekali matanya menjeling ke arahku. Dalam asyik berbual dia mengawasi Sarah dengan begitu teliti sekali. Mungkin curiga dengan niatku mendekati tubuh kecil itu. Lega rasanya di hati bila dia hanya memandang dari tempat duduknya kira-kira 20 meter dari tempat aku berdiri.
“Adik...,” tegurku perlahan.
Sarah berpaling kepadaku. Dan, demi mata itu tertancap ke dalam mataku, sejuta rasa yang sukar aku mengertikan menggetar tubuhku. Terasa sesak nafasku seketika memandang ke dalam mata itu. Air mata bahagia lantas bergenang di tubir mata. Setelah sekian lama, kini aku kembali dapat bertentang mata dengannya. Kalau dulu dia cuma tersenyum bila diagah. Berbicara mesra dengan bahasa bayinya yang sedikitpun tidak aku mengertikan. Dengan wajah mulus seorang bayi kecil yang cukup bersih dan suci dari sebarang dosa dan noda. Dan kini wajah kecil itu masih lagi kelihatan bersih dan suci. Membuatkan aku terpaku, tidak mampu berbuat apa-apa.
Dia tersenyum kepadaku. Perlakuan sepontan yang menyebabkan aku kehilangan kata-kata. Terpaku aku menatap wajahnya. Matanya bersinar lembut bagaikan kolam yang tenang airnya. Bagaikan sempurna hidup ini hanya dengan menatap ke dalam matanya. Damai aku rasakan sebentar tadi berkocak hebat. Tidak aku menyangka begini hebatnya debaran di hati yang aku rasakan saat ini.
Kalau boleh ingin sekali aku memeluknya di situ. Tetapi, aku tidak mahu membuatkan dia terkejut dan menangis. Aku tidak mahu kenaifan di matanya bertukar kepada rasa takut dengan tindakan drastikku. Saat ini, biarlah nikmat ini aku rasakan satu persatu. Aku juga tidak mahu menarik perhatian pengasuhnya. Bimbang jika perlakuanku yang keterlaluan itu akan menyebabkan Sarah tidak lagi dibenarkan ke mari. Mana mungkin aku mampu menahan sedih dan kecewaku jika aku tidak lagi dapat menatap wajahnya. Aku masih belum lagi punya kekuatan untuk berhadapan dengan ayahnya. Aku... tidak mahu berhadapan dengannya. Tidak pada saat ini.
Perlahan aku duduk bertinggung di sebelahnya. Mata kami kini searas. Dia terus menatap ke dalam mataku. Membawa sejuta rasa bahagia di hatiku. Masa bagaikan terhenti seketika. Dan di dalam ruang waktu itu, hanya aku dan dia sahaja yang ada di situ.
“Mama....,” ucapnya lembut.
Terkesima aku dibuatnya. Hampir luluh jantungku mendengarkan ucapan kalimah yang amat berharga itu. Air mata yang bergenang tadi, kini menitis jatuh di pipi. Bagaikan sesak nafasku saat itu. Dan bicaraku juga jadi bungkam. Dia kenal siapa diri ini? Adakah kalimah itu diucapkan secara sedar? Atau hanya meniti di bibirnya tanpa dimengertikan maksudnya?
“Unie...,”
****
Tanganku Kak Reen genggam erat sekali. Segera rasa resahku tadi hilang serta merta. Sesungguhnya dia tidak membenci diri ini. Dan sesunguhnya sedikitpun dia tidak marah kerana aku berada di sini, bersama Sarah.
“Sejak bila Kak Reen tahu yang Unie selalu datang ke mari?” tanyaku perlahan.
Aku tertangkap kini. Akhirnya apa yang aku ingin hindari diketahui juga oleh Kak Reen. Dan pasti... aku yakin pasti... selepas ini Abang Izwan juga akan tahu tentang perkara ini. Kebimbangan menyelinap masuk memenuhi ruang hati. Mampukah aku menghadapi saat itu nanti? Berhadapan dengannya dalam keadaan marahnya?
“Dah lama...,”
Dia mengeluh perlahan. Aku juga bagaikan tidak mampu untuk meneruskan bicara. Menunggu dia meneruskan kata-katanya.
“Bila Aida cakap ada orang selalu perhatikan Sarah bermain, akak dah syak, mesti orang itu Unie. Sejak mak cakap yang Unie dah balik dan minta alamat dan nombor telefon Kak Reen, akak dah tahu, mesti Unie akan datang jumpa akak. Tak sangka sampai begini lama, Unie masih lagi belum hubungi akak,”
Terperanjat aku mendengarkan kata-katanya itu. ya, sepatutnya aku sedar bahawa Mak Ngah pastinya akan menceritakan hal kepulanganku kepadanya. Dia tentu dapat tahu dari Mak Ngah. Tetapi, adakah Abang Izwan juga tahu? Tidakkah dia marah?
“Unie takut kak... Bimbang nanti akak tak akan benarkan kami berjumpa. Takut nanti .... Abang Izwan buat sesuatu, supaya Unie tak dapat tengok Sarah lagi. Masa jumpa Mak Ngah dulu, dia kata Abang Izwan betul-betul marah pada Unie,” kataku dengan teragak-agak. Untuk menyebut nama lelaki itupun terasa amat benci sekali.
Kak Reen terdiam. Dia memandang tepat ke dalam mataku. Mengeluh perlahan sambil mengangguk. Satu perlakuan yang mengesahkan apa yang dikatakan oleh Mak Ngah.
“Memang dia marah sangat pada Unie. Inipun dia tak tahu yang Unie datang intai Sarah. Kalau dia tahu, mesti dia tak benarkan Aida bawa Sarah ke sini,”
“Akak... tak marah... Unie jumpa Sarah?”
“Untuk apa akak marah Unie? Akak tak boleh pisahkan antara seorang anak dengan ibunya kan? Walau apa pun yang terjadi, dia tetap anak Unie kan?” ucapnya dengan deraian airmata yang laju mengalir di pipi.
Aku turut sama menangis. Terkejut sungguh bila mendengarkan kata-kata itu. Sesungguhnya aku selama ini telah salah sangka padanya. Selama ini aku benar-benar menyangka yang dia yang menyebabkan aku dan Abang Izwan terpisah. Tapi, kata-katanya itu menyedarkan aku pada satu hakikat. Kak Reen pastinya tidak salah dalam hal ini. Bukan dia yang memisahkan kami. Bukan dia yang mempengaruhi Abang Izwan seperti yang dikatakan oleh Suzana apabila surat cerai itu aku terima lama dulu. Tidak mungkin dia puncanya jika setulus ini kata-katanya.
“Selama ni Kak Reen rasa bersalah sangat bila biarkan Abang Izwan ceraikan Unie dulu. Langsung tak sangka dia akan buat macam tu. Bila ingatkan Unie yang duk kat sana seorang-seorang, Kak Reen rasa berdosa sebab tak nasihatkan dia. Tentu Unie sedih sangat masa tu kan?”
“Separuh mati kak...,” jawabku perlahan. Airmataku seka lagi. “Sampai hari ni... sakitnya masih ada kat sini,” kataku sambil meletakkan tapak tanganku di dada.
“Unie betul-betul cintakan dia?” dia bertanya perlahan, meminta kepastian.
“Siapa yang tak cintakan suaminya kak..., walau sebusuk manapun dia, sejahat mana pun dia, seorang isteri wajib mencintai suaminya kan? Macam akak, walau macam mana derita pun akak bila dia kahwin dengan Unie, akak tetap cintakan dia kan?”
“Unie masih cintakan dia sekarang?”
Aku diam, tidak mampu berkata-kata. Cintakah aku padanya? Masih adakah perasaan itu pada lelaki ini yang satu hari dulu amat aku sanjungi sebagai seorang suami? Yang sesungguhnya telah merobek segenap kepercayaanku terhadap insan bernama lelaki. Yang membuatkan aku tidak lagi berani untuk meneruskan masa depanku dengan kaum sepertinya. Saat itu wajah Umar Rafiki melintas di depan mata. Lalu aku menggelengkan kepalaku perlahan.
“Cinta Unie dah mati kak. Kepercayaan Unie dah hilang untuk lelaki. Unie tak akan percaya lagi pada lelaki,”
Kak Reen terdiam.
“Cuma sekarang ni, Unie nak tahu kenapa kak? Kenapa dia tiba-tiba ceraikan Unie?Apa salah Unie sampai tiba-tiba aje dia buat keputusan macam tu?”
“Akak tak tahu Unie. Akak dah tanya dia, tapi... dia tak beritahu sebabnya. Akak rasa puncanya berlaku masa dia ke sana. Dia rahsiakan apa yang berlaku masa dia kat sana. Mulanya dia kata, dia nak habiskan masa sebulan dengan Unie. Cadangnya nak bawa Sarah sekali, tapi kebetulan masa tu Sarah kena demam campak. Jadi dia pergi sendiri. Tapi tak sampai seminggu dia dah balik semula. Dia murung sangat. Bila Kak Reen tanya kenapa, dia diam. Apa sebenarnya yang berlaku masa tu Unie?”
Aku diam seketika. Kata-katanya itu mengiakan apa yang diberitahu oleh Mak Ngah kepadaku dulu.
“Unie tak tau kak... Unie tak jumpa pun dengan dia. Sebenarnya...bila dia pergi? Kenapa dia tak beritahu Unie dia nak ke sana?”
“Masa tu Unie tengah cuti semester. Akak ingat lagi... dia minta akak tanya bila Unie cuti. Lepas tu dia book tiket ke sana. Katanya nak buat surprise untuk Unie,”
“Kalau masa cuti semester kali pertama kat sana dulu, Unie ikut penasihat Unie pergi cari maklumat untuk kajian Unie. Masa tu kami pergi ke kilang-kilang dan industri-industri untuk edarkan soal selidik dan dapatkan data untuk kajian tu. Kami pergi dengan kawan-kawan, enam orang semuanya. Lebih kurang dua minggu kami ke sana. Sambil tu kami jalan-jalan, melawat sekitar kawasan menarik kat Australia tu. Unie tak tahu pun dia nak pergi. Dan, masa tu Unie rasa macam dah beritahu Kak Reen dalam facebook yang Unie nak pergi kan? Dia tak tau tahu ye?”
Air mata yang mengalir sudah reda semula. Mataku terus memandang pada Sarah yang masih asyik bermain gelongsor. Persoalan dalam hati cuba aku cari jawapannya. Namun aku buntu lagi. Apa yang berlaku sebenarnya di sana?
“Entahlah Unie, akak pun lupa pasal perkara tu. Mungkin masa tu akak lupa nak beritahu dia. Sebab tu akak rasa bersalah sangat sekarang ni,”
“Pelik ye... Apa yang berlaku sebenarnya masa tu? Kebetulan masa tu cuti, jadi ramai yang tak ada kat kampus. Ada yang balik ke Malaysia, ada yang pergi jalan-jalan. Jadi tak ada sesiapapun yang beritahu Unie yang dia datang masa tu. Sampailah masa Unie pergi jumpa Mak Ngah hari tu. barulah Unie tahu yang dia pernah ke sana,”
“Mesti ada sesuatu yang berlaku masa tu kan?” kata Kak Reen penuh tanda tanya. Kelihatannya seperti dia serba salah.
Ya, timbul tanda tanya di hatiku. Tanda tanya yang hanya boleh dirungkai oleh Abang Izwan. Tiada siapapun yang tahu apa yang berlaku ketika itu. Kalaupun ada yang tahu, pastinya orang itu mendiamkan dirinya atas sesuatu sebab. Ah... buntu aku untuk memikirkannya.
“Kak, satu lagi yang Unie nak tahu,” tanyaku dalam rasa serba salah. Namun aku perlu tahu tentang ini. Aku tidak mahu berteka-teki tentang perkara ini.
“Apa dik…?” Tanya Kak Reen kepadaku semula.
“Emmm… betul ke macam yang akak cakap dalam surat akak pada Unie dulu? Betul ke… selama ni dia tipu Unie, cakap yang dia cintakan Unie semata-mata nak perangkap Unie supaya kahwin dengan dia? Sedangkan … dia sebenarnya nakkan anak aje? Bila dah dapat Sarah, dia tak perlukan Unie lagi? Macam yang akak cakap dalam surat tu? ” kataku menuntut penjelasan.
Kelihatan Kak Reen resah. Dia bagaikan serba salah, tidak mampu untuk berkata-kata seketika. Tiba-tiba dia memelukku. Pecah tangisannya saat itu. Membawa rasa hairan dan terkejut yang amat sangat di hatiku melihatkan perlakuannya itu.
“Maafkan Kak Reen Unie, masa tu akak tak tahu apa nak cakap. Unie desak akak nak tau punca dia ceraikan Unie. Abang Wan pulak marahkan akak bila dia tahu Unie berhubung dengan akak. Dia suruh akak cakap apa aje supaya Unie berhenti ganggu kami. Dan... masa tu, akak tak tahu nak cakap apa. Jadi.... akak tulislah apa yang terlintas di hati akak masa tu..., maafkan akak Unie....,” katanya dalam tangis yang kian menjadi-jadi.
Sekali lagi aku terkejut mendengarkan kata-katanya itu. Benarkah begitu? Benarkah Kak Reen berdusta tentang perkara itu? Cukup tidak aku percaya dengan kata-katanya itu. Ah ... aku sendiri sudah tidak tahu apa yang patut aku percayakan lagi.... Semuanya buntu saat ini.
Kehadiran Sarah yang tiba-tiba naik ke ribaanku mengejutkan kami. Di tangannya tergenggam sebatang aiskrim. Dia menyuakan kepadaku, meminta aku membuka plastik aiskrim tersebut. Terkejut dengan perlakuan sepontan itu, menyababkan aku berpaling kepada Kak Reen.
“Mama buka...,” ucapnya manja. Sambil matanya merenungku penuh mengharap.
Aku lantas memeluk tubuh kecil itu sambil turut sama menangis. Terharu kerana Kak Reen membenarkan anak ini mengenaliku sebagai mamanya. Kak Reen tersenyum pahit sambil menyeka airmatanya.
“Sebab rasa bersalah biarkan Abang Izwan ceraikan Unie, akak buat keputusan supaya Sarah kenal Unie. Akak harap sekurang-kurangnya Unie tak terus marahkan akak,”
Dan aku menangis lagi. Terharu mendengarkan kata-katanya itu Terharu dengan pengorbanannya itu. Dia sebenarnya boleh menyembunyikan hakikat ini dari Sarah. Dia sebenarnya mampu untuk membiarkan Sarah terus menyangkakan bahawa dialah ibunya, sekurang-kurangnya hingga Sarah sudah cukup besar untuk memahami keadaan ini. Namun dia tidak melakukan itu. Ah... aku silap lagi bila aku mencurigai Kak Reen. Silap lagi....