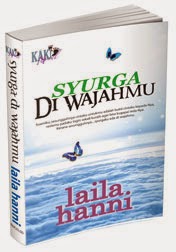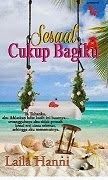Bab 32
Selesai bersolat dan berdoa aku menyalami kedua wanita tersebut, Kak Odie dan gadis yang lebih muda itu. Sememangnya kami belum lagi diperkenalkan secara rasmi. Terasa kekok untuk berbicara dalam keadaan begini. Aku memandang pada Rafiki, mengharapkan dia memperkenalkan kami. Dan saat itu aku sedar yang dia juga sedang asyik memandang padaku.
“Unie, saya kenalkan, ini mummy saya, Puan Rogayah” katanya sambil dia memeluk erat bahu wanita yang sedang tersenyum memandangku itu. Dia kemudiannya mengalihkan pandangannya kepada emaknya sambil tersenyum kepada wanita itu. Nampak mesra sekali.
Ada persamaan pada raut wajah kedua mereka. Walaupun mereka tidak seiras, apabila tersenyum tiada siapa yang dapat menyangkal bahawa mereka ada pertalian persaudaraan. Aku menghulurkan senyuman yang seikhlas mungkin untuk membalas senyuman manis dari wanita itu.
“Mummy, ini Munirah. Akhirnya sampai juga hasrat mummy nak kenal dia kan?” katanya kepada emaknya.
Sungguh aku terperanjat mendengarkan kata-kata itu? Apa maksudnya melontarkan kata-kata itu? Hasrat? Mummynya ada hasrat untuk menemui diri ini? Adakah dia mengenaliku? Kalau begitu dari siapa dia kenal diri ini? Dan sejak bila? Bukankah ini baru pertama kali kami bertemu? Ah... hairan, sungguh hairan.
“Apa khabar puan?” tanyaku perlahan.
“Baik... alhamdulillah. Munirah kan tadi mummy dah cakap, jangan panggil puan. Panggil mummy, semua orang panggil macam tu. Lagi mesra rasanya kan?” katanya dengan senyuman yang makin melebar.
Aku jadi malu sendiri. Berada bersama wanita ini aku boleh jadi lupa diri. Senyumannya itu membuatkan aku merasa cukup dihargai.
“Yang ini pula, Tok Wan saya. Telinga dia dah tak dengar. Tapi kalau bercakap dengan dia, dia boleh faham bila tengok bibir kita,” katanya sambil menarik wanita yang lebih tua itu ke dalam dakapannya.
Dia kini berada di antara keduanya. Ya, jelas sekali adanya pertalian saudara antara mereka bertiga. Raut wajah Puan Rogayah saling tak tumpah dengan wajah Tok Wan. Mesra dan sering tersenyum.
“Tok Wan sihat?” tanyaku dengan suara yang lembut. Cuba bercakap perlahan supaya wanita tua yang sering tersenyum manis itu mudah memahami kata-kataku.
“Sihat...,” katanya ringkas. Kemudian dia berpaling pada Rafiki. “Pandai Rafiki cari... cantik...,” Katanya dengan nada lembut memuji.
Rafiki ketawa kuat sekali, disambut oleh mereka yang ada di situ. Riang sungguh dia saat itu. Berbeza sungguh dengan sikap merajuknya petang tadi. Cuma aku sahaja yang tidak mengerti maksud tawa mereka itu.
“Ehem..ehem... dah lupa pada Adah...?” gadis yang menjadi tanda tanya di hatiku itu bersuara sambil menarik tangan Rafiki denga mesra.
Aku hanya memandang kemesraan itu dengan satu perasaan yang tidak aku mengertikan. Terasa seperti ada tangan kasar yang meramas hati ini melihatkan perlakuan mesra itu. Adakah aku cemburu melihatkan adengan mesra begitu? Cemburu? Munirah...?
Rafiki ketawa lagi. Lantas dia meraih jari jemari gadis itu dan menariknya dekat kepadaku.
“Unie kenal tak budak manja ni?” dia bertanya padaku.
Matanya kembali mengelus lembut di wajahku. Lantas cepat-cepat aku mengalih pandang ke wajah gadis di sebelahnya. Cuba menenangkan hati ini yang kembali berkocak laju. Cukuplah Umar Rafiki, jangan goda hatiku lagi. Hentikanlah godaanmu itu.
Aku mengamati wajah gadis itu.
“Siapa ye? Kita pernah jumpa ke?”
Dia mengangguk laju. Sambil bibirnya mengukir senyum mengusik, dia berkata,
“Emm... empat tahun lepas...Sampai hati Kak Unie dah lupakan Adah. Pak Ngah ni akak tak lupa pun....,” matanya menjeling kepada Rafiki. Membawa tawa bahagia di hati lelaki itu. Jelas terserlah perasaan itu di wajahnya.
Berkerut dahiku cuba untuk mengingatkan peristiwa empat tahun lepas. Pertemuan pertama aku dengan Rafiki dan... bersamanya seorang gadis. Bermakna..., dia gadis yang bersamanya waktu itu?
“Unie, kenalkan my niece... Syuhadah. Atau, manjanya... Adah,”
Aku senyum padanya. Cukup bersalah aku rasakan bila aku sedikitpun tidak mengenalinya. Sungguh dia sudah banyak berubah dari dulu. Ketika itu dia tidak bertudung. Memang sukar untuk aku mengenalinya yang sedang memakai telekung sebegini.
“Masa tu... Adah baru dapat surat panggilan ke UPM. Saya bawa dia ke Kenny Rogers untuk raikan kejayaan dia tu. Tak sangka pulak hari ada yang marah pada kami,”
“Nasib baik ada yang datang marah. Lepas pada itu, ada orang tu… dok gila bayang tau kak. Bila Adah cerita yang Adah pernah tengok akak kat UPM, dia suka sangat. Siap nak berkenalan. Siap minta Adah bawak dia ke UPM. Tapi bila Adah beritahu dia yang akak dah kahwin…, tengah mengandung, siap frust menonggeng kak,”
Kata-kata yang polos itu membuatkan aku tersentap. Sedikit demi sedikit hakikat diri ini datang berpaut kembali pada hati ini. Hilang pergi kedamaian dan kegembiraan yang aku rasakan sebentar tadi. Aku menarik nafas panjang.
“Adah....,” sampuk Rafiki pantas. Mungkin dia menyedari apa yang terlintas di hatiku saat itu.
“Oops.... maaf kak... maaf....Adah tak sengaja kak...,”
Puan Rogayah menampar lembut bibir Syuhadah. “Lain kali, nak cakap tu... pandang-pandang la sikit... Jangan ikut sedap mulut aje,” marahnya pada gadis itu.
“Sorrylah nek...,” rengek Syuhadah manja.
Puan Rogayah berpaling kepadaku. Senyum kembali meniti di bibirnya.
“Unie, jangan kecil hati ye? Mulut Syuhada ni memang macam tu. Celupar betul,”
****
Hal itu akhirnya dilupakan begitu sahaja. Mereka kelihatan seperti merasa bersalah dengan keadaan yang membuatkan aku sedikit tersinggung. Dan untuk menjaga hati mereka aku juga cuba melupakan perkara itu. Cuba untuk bermesra dengan keluarga yang kelihatan cukup bahagia itu. Rupa-rupanya Syuhadah sekarang masih lagi sedang belajar di UPM di Fakulti Pengajian Alam Sekitar.
Bila ayahnya pulang dari masjid bersama dengan adik lelakinya yang paling bongsu, aku dapati bahawa keluarga ini memang cukup lengkap segalanya. Ayahnya juga mesra orangnya. Dia melayanku denga baik sekali. Bertanyakan itu dan ini tentang diri ini. Bila aku ditanya mengenai keluargaku aku menceritakan segalanya. Dan mereka cukup bersimpati dengan diriku yang telah menjadi yatim piatu sejak kecil lagi. Kata-katanya memberi semangat untuk aku teruskan kehidupanku. Namun sepanjang waktu itu mereka sedikit pun tidak menyentuh lagi mengenai statusku, walaupun aku tahu mereka semua telah arif mengenai perkara itu.
Selesai makan malam aku minta diri untuk pulang. Terasa cukup penat diri ini. Terlalu banyak yang berlaku dalam masa satu hari ini. Terlalu banyak rahsia yang aku ketahui hari ini. Semuanya begitu mendebarkan. Semuanya mampu menggugat ketenangan yang aku rasakan selama ini.
“Eh, tidur kat sini sajalah malam ni. Esokkan nak pergi lagi dengan Rafiki. Boleh terus pergi aje dari sini,” kata emaknya.
“Em... tak payahlah makcik. Saya... tak biasa tidur kat tempat lain,” terkejut sekali aku mendengarkan pelawaannya itu.
Sudahlah mereka melayanku dengan baik. Aku terasa malu sebenarnya dengan layanan yang cukup baik begini. Kini mempelawa aku tidur pula di rumah mereka. Sesuatu yang sungguh di luar jangkaanku.
“Jangan balik lagilah kak... belum puas berbual dengan akak,” rengek Syuhadah manja.
“Tak boleklah Adah. Lagipun Kak Unie tak ada baju,” aku memberikan alasan.
“Hei... baju Adah kan ada. Badan kitakan sama aje saiznya. Janganlah balik kak... Pak Ngah, janganlah hantar Kak Unie balik lagi. Boraklah dulu...,” rayu Adah agi sambil memandang ke wajahku penuh mengharap.
“Ialah Unie, tidur aje kat sini. Unie boleh tidur dengan Adah,” kata Pak Cik Safuan bagaikan memberi kata putus.
“Em... terima kasih lah pakcik, makcik... Tapi saya rasa tak bolehlah. Bukan tak sudi tapi saya rasa tak selesa macam ni,” kataku dengan sopan kepada kedua orang tu itu, tidak mahu rasanya aku menyinggung perasaan mereka. Kemudian aku berpaling kepada Syuhadah. “Adah, lain kali kita boleh borak lagi ye. Tapi malam ni akak kena balik...,”
Aku malu sebenarnya dengan keadaan ini. Tidak pernah aku mendapat perhatian sebegini dalam hidupku. Kemesraan mereka membuatkan aku merasa seperti diterima dalam keluarga ini. Sesuatu yang amat aku impikan selama ini. Sesuatu yang mengisi lompang dalam hidupku ini. Jauh dari suasana yang aku alami sejak aku berkahwin dengan Abang Izwan lama dulu. Dan jika mampu aku inginkan suasana sebegini terus ujud dalam hidupku. Tidak mahu kehilangan kebahagiaan yang aku rasakan ini selama-lamanya.
“Pak Ngah... do something please... Jangan hantar Kak Unie balik dulu, please....,”
“Adah... tak bolehlah macam tu. Kita kena hormat pada Kak Unie. Mungkin dia ada hal lain kut. Atau dia penat dan tak selesa beralih tempat tidur,” kata Rafiki memujuk anak saudaranya itu. Syuhadah sudah mula menarik muka. Panjang sekali muncungnya menunjukkan rajuknya.
“Emm... lain kali Kak Unie datang lagi ye. Lagipun Adah boleh datang ofis Kak Unie bila ada masa terluang,” aku pula yang memujuk.
“Kalau macam tu, hari minggu ni, Unie kena datang lagi ke sini. Mummy pun tak puas lagi berbual dengan Unie,” kata Puan Rogayah. Aku tersentap seketika. Mana mungkin aku menerima pelawaan ini sehinggakan aku tidak dapat pergi untuk bersama dengan Sarah. Tetapi aku rasakan cukup tidak tergamak untuk menolak pelawaan ini.
Aku memandang kepada Rafiki untuk mendapatkan pengertiannya. Dari riak wajahnya aku tahu dia mengerti. Dia mengangguk perlahan membuatkan aku merasa sedikit lega.
“Mummy, tadi Unie ada beritahu Fik yang dia ada hal sikit hujung minggu ni, betulkan Unie?”
Laju aku menganggukkan kepala tanda setuju.
“Mungkin dia boleh datang lain kali. Unie tahu, kat rumah kami ni setiap hari Ahad akhir bulan, macam Hari Raya. Masa tu semua abang, kakak dan adik-adik saya balik. Riuh rendah tau. Seronok. Mungkin masa tu Unie boleh datang, boleh kenal-kenal dengan semua adik beradik saya,”
“Haah... betul tu. Unie datang ye hari Ahad terakhir hujung bulan ni. Boleh kenal dengan semua. Mummy harap sangat tu tau….,” kata Puan Rogayah dengan riang sekali.
Dan akhirnya aku terpaksa akur dengan permintaan mereka itu. Aku telah dilayan dengan baik sekali. Tidak tergamak rasanya di hati untuk menolak pelawaan mereka.
*****
“Sebenarnya sejak bila keluarga awak kenal saya?” aku memberanikan diri untuk bertanyakan soalan itu sebaik sahaja MPVnya bergerak meninggalkan kawasan perumahan mewah di Damansara Heights itu.
Rafiki senyum melihatkan aku yang tidak sabar-sabar untuk bertanyakan soalan itu. Mungkin sejak dari tadi dia sudah menjangka aku akan bertanyakan tentang perkara tersebut.
“Sejak... pertama kali saya jumpa orang yang matanya cantik sangat…., Yang….. ada tahi lalat kat bawah bibir kirinya tu…. Yang…. marah-marah sebab saya ambil meja dia kat Kenny Rogers dulu... Yang…. sedikit pun saya tak mampu buang jauh dari ingatan saya sejak lama dulu….,” ucapnya lambat-lambat.
Terdiam aku mendengarkan kata-katanya yang jadi sedikit romantis. Membuatkan debaran kembali singgah di hati saat ini.
“Tahu tak? Lepas kita jumpa dulu saya menyesal sebab tak cuba berkenalan dengan Unie. Masa tu saya tak sangka yang saya akan jadi angau macam tu. Dan bila satu hari Adah balik dari kampus, dia beritahu dia dah jumpa Unie, saya rasa gembira sangat. Kebetulan kawan sebiliknya dulu student Unie,”
“Oh... sebab tu Unie tak kenal dia. Rupanya melalui kawan...,”
“Ya.... Tapi lepas tu dia beritahu yang Unie dah kahwin. Unie tengah mengandung. Dan asyik cuti aje. Kawan dia beritahu yang Unie ni kuat alahan masa mengandung. Selalu kena masuk hospital, selalu MC dan tak dapat datang kerja. Masa tu saya frust sangat. Baru aje jumpa yang kita dah berkenan, rupa-rupanya dah jadi isteri orang,”
Aku menarik nafas panjang.
“Bila kita jumpa lagi kat dalam komuter tu…, kenangan lama datang balik. Tapi saya akur, Unie bukan jodoh saya. Unie… dah bersuami, dah ada anak... Masa tu… saya belum tahu yang Unie dah... putus dengan suami Unie tu,” katanya perlahan-lahan seolah-olah cuba untuk tidak menyinggung perasaanku.
“Tapi bila kita jumpa lagi kat kondomanium kita…, saya rasakan ada sesuatu di sebalik pertemuan-pertamuan kita tu. Saya rasa… ia bukan satu kebetulan. Allah memang nakkan kita berjumpa. Mungkin…, jodoh kita kuat, hinggakan kita dipertemukan semula. Dan bila saya dapat tahu yang Unie dah berpisah dengan suami, saya jadi lebih yakin yang… Allah memang nak satukan kita. Sebab tu.... saya beritahu Kak Pah dan Suzana yang saya sukakan awak,”
“Suzana?”
“Ya, dia yang ceritakan segala-galanya tentang awak pada saya,”
Aku menelan air liurku. Terkedu lagi. Rupa-rupanya masih ada kejutan yang aku belum tahu lagi. Selama ini aku hanya menyangka Kak Pah yang membawa cerita. Langsung aku tidak menyangka yang Suzana juga ada peranannya dalam semua ini. Ah... sungguh aku tidak percaya.
“Unie,” serunya apabila melihatkan aku lama mendiamkan diri.
Aku berpaling menatap wajahnya. Kami bertatapan, lama sekali. Kebetulan ketika itu MPVnya diberhentikan kerana berada di persimpangan lampu trafik.
“Saya betul-betul serius dengan apa yang saya katakan petang tadi,”
“Huh.... ,” keluhku sambil ketawa perlahan.
“Kenapa Unie ketawa. Sinis sangat, Unie tak percaya,”
“Sanggup ke awak? Nak ke awak hadapi semua ni dengan saya. Awak ingat senang ke? Dah hampir lima bulan sejak saya balik, saya cuba kumpul kekuatan untuk bersemuka dengan dia. Tapi sampai hari ni saya belum berani. Saya bimbang nanti kalau dia tahu, dia akan terus tak benarkan Sarah keluar. Dia mungkin akan halang saya dari jumpa Sarah. Dia mungkin akan sekat kebebasan Sarah. Anak saya tu kecil sangat lagi untuk mengerti semua ni. Dan saya.... kalau itu yang berlaku, saya... tak tahu apa yang patut saya lakukan lagi. Saya tak sanggup terus kehilangan Sarah,” kataku perlahan.
Dia diam, langsung tidak memberikan apa-apa reaksi dengan kata-kataku itu. Seolah-olah tidak mendengar kata-kataku itu. Hinggakan aku merasakan seperti tidak yakin sama ada betulkah aku yang berkata-kata sebentar tadi. Meluahkan apa yang terbuku di hati. Dan dia terus membisu, tanpa kata. Membuatkan aku turut sama membisu.
Kami akhirnya tiba ke destinasi kami. MPVnya diberhentikan di tempat parkirnya. Namun sedikitpun kami tidak berganjak dari tempat duduk kami. Terasa seolah-olah tidak mahu berpisah. Terlalu banyak yang ingin aku katakan padanya. Terlalu banyak yang ingin aku kongsikan bersamanya. Menyedari hakikat itu, aku terasa seperti terhimpit dengan rasa bersalah. Layakkah aku???
“Tapi sampai bila awak nak terus jumpa dia secara sembunyi-sembunyi macam ni?” Tanya dia tiba-tiba.
Ah… dia dengar rupa-rupanya akan kata-kataku tadi. Sangkaku dia tidak mendengar dek kerana sikapnya yang membisu. Rupa-rupanya tidak, dia mendengar sebanarnya. Namun tidak mendesak supaya aku terus menceritakannya. Lama aku mengambil masa untuk menjawab soalannya itu.
“Sampai bila-bila.... sampai saya cukup kuat nak hadapi Abang Izwan,” akhirnya aku bersuara.
“Itu nama dia ye?”
Aku berpaling kepadanya. Mengangguk lesu.
“Pada mulanya saya pelik tengok awak selalu keluar setiap hari Ahad. Bila saya berbual dengan Suzana, barulah saya tahu masalah awak tu. Jadi saya ekori awak. Saya nak tengok sendiri apa yang awak buat. Awak sepatutnya jumpa dia. Bincang dengan dia baik-baik,”
“Huh.. nak berbincang dengan Abang Izwan? Awak tak kenal dia. Dia bukan jenis manusia yang boleh diajak berbincang. Dia... ego dia tinggi sangat. Kalau tidak, takkan lah dia ceraikan saya tanpa sebarang sebab. Dia tak pernah mahu berbincang dengan saya. Tak pernah beri peluang untuk saya tahu apa salah saya. Bila ditanya dia kata saya curang. Saya sendiri tak tahu bila atau dengan siapa saya curang. Dia... kejam sangat,” kataku sambil menahan sebak.
“Mungkin Unie boleh rujuk peguam syarie?”
“Saya tak mampu nak bayar khidmat lawyer Rafiki,”
“Mungkin awak boleh dapatkan khidmat nasihat Biro Guaman?”
“Saya dah pergi jumpa mereka,”
“Apa kata mereka?”
“Mereka kata kes saya ni susah sikit nak menang sebab dalam kes ini Sarah sudah dalam keadaan baik. Kebajikan dia dah terjaga bila dia tinggal dengan ayahnya. Memang sebenarnya hak penjagaan anak yang belum mumaiyiz ni lebih kepada pihak ibu, tetapi keadaan saya yang belum setabil ni, mungkin akan menjejaskan kebajikan Sarah. Dalam hal penjagaan anak ni, mahkamah selalu pentingkan kebajikan anak itu. Mereka nasihatkan supaya saya tidak menuntut hak penjagaan. Lebih baik kalau saya bincang baik-baik dengan Abang Izwan supaya saya diberi peluang untuk berjumpa Sarah. Kalau dia setuju, saya tak perlu turun naik mahkamah hanya untuk menghadapi kekalahan,”
Lama dia diam. Mungkin sedang memikirkan sesuatu.
“Kalau saya bantu awak? Kita cari peguam? Saya boleh bayarkan...”akhirnya dia berkata perlahan.
Terkejut aku mendengarkan kata-katanya itu. Cepat-cepataku menggelengkan kepalaku.
“Jangan... jangan.... saya... tak akan terima itu dari awak. Saya tak akan.... saya ulang sekali lagi... tak akan... terima budi awak,”
Dia mengeluh perlahan. Dia mengetap bibirnya. Matanya terus tertancap ke wajahku.
“Awak nak pergi jumpa dia… maksud saya, Izwan?” tanyanya akhirnya.
“Saya... belum berani lagi. Macam yang saya katakan tadi, saya bimbang kalau saya jumpa dia, lepas ni saya langsung dah tak boleh jumpa Sarah lagi.,”
“Saya temankan awak pergi jumpa dia?”
Aku merenung ke wajahnya. Cuba untuk memahami maksudnya. Tidak tersalah dengarkah aku kali ini? Atau mungkin dia cuma bergurau?
“Saya serius,”
“Kenapa?”
“Masa pertama kali saya dapat tahu yang Unie dah berpisah dengan dia hari Unie pindah masuk ke apartmen kita ni, saya dapat rasakan kesedihan yang Unie rasakan tu. Saya rasa simpati sangat. Sampaikan saya jadi lupa diri. Tidak sepatutnya saya memegang tangan Unie masa tu kan? Tapi, waktu tu saya rasa saya perlu buat sesuatu untuk buang riak sedih di wajah Unie tu. Saya betul-betul nak bantu Unie, saya nak hapuskan kesedihan Unie tu,”
Aku terdiam. Aku tidak mampu untuk berfikir apa-apa saat itu. Semuanya jadi buntu.
“Boleh tak Unie? Izinkan saya jadi pendamping Unie. Bila dengar cerita Suzana tentang kesedihan dan kesengsaraan Unie selama ni, saya turut rasa sedih. Saya nak Unie bahagia. Dan…, saya nak bahagia dengan Unie,”
Aku menarik nafasku panjang-panjang. Cukup terkejut dengan pengakuannya itu. Memang selama ini aku bagaikan dapat meneka perasaannya terhadapku. Namun, kata-katanya yang cukup tegas kali ini membuatkan aku tertanya-tanya. Ada keikhlasankah dalam kata-kata itu?
“Kenapa awak kata macam tu? Awak lelaki yang sempurna. Awak ada segala-galanya. Kenapa awak nak susahkan diri untuk saya. Kenapa awak nak dampingi orang yang malang macam saya? Mummy awak tentunya tak suka kan? Saya janda Rafiki, tak punya apa-apa. Cuma yang ada, kesedihan dan kekecewaan,” ucapku lembut.
Mataku terus merenung ke hadapan. Di celah-celah kegelapan malam kelihatan permandangan indah kawasan perumahan yang berdekatan begitu luas terbentang. Namun kerdipan lampu-lampu neon dari kawasan perumahan itu langsung tidak mampu menandingi keindahan kerdipan bintang-bintang di langit. Sungguh indah dan mendamaikan ciptaan tuhan itu. Malangnya kedamaian seindah itu sedikitpun tidak mampu untuk melegakan perasaanku saat ini.
“Sebab itu saya nak bersama Unie. Saya nak buang semua kesedihan dan kekecewaan itu,”
Cukup aku terharu dengan kata-katanya itu. Airmata mula bergenang di tubir mata. Sungguh tidak aku menyangka ini akan berlaku. Sungguh aku tidak percaya ada hati yang cukup mulia yang ingin melihat aku kembali bahagia.
“Kalau Unie sudi, boleh tak terima saya? Saya nak hubungan yang halal dengan Unie. Saya nak jadi suami Unie, nak kembalikan kebahagiaan yang sekian lama dah hilang dalam hidup Unie,”
Ya Allah, benarkah semua ini? Benarkah apa yang dikatakan ini? Bermimpikah aku? Sering dalam hati ini menafikan daya tarikan yang ada antara kami. Sering aku cuba lari dari hakikat bahawa aku sudah terpikat kepadanya. Hanya kerana menyedari siapa diri ini. Tapi kini, kata-kata itu tadi keluar terus dari bibirnya yang cukup menawan itu. Yang sering aku dambakan kehangatannya dalam angananku.
“Unie?”
“Tapi... perasaan awak tu salah. Saya, tak layak untuk awak,” jawabku perlahan.
“Tak ada yang salahnya Unie, tak ada. Jangan nafikan tarikan antara kita. There’s a strong chemistry between us. Saya dapat rasakan. Dan saya tahu Unie juga dapat rasakan,”
“Tapi... keluarga awak? Mummy dan ayah awak?”
“Kami dah bincang tentang perkara ini. Dah lama dah, sejak saya jumpa Unie semula,” katanya lagi lembut sungguh bicaranya itu.
Bagaikan memujuk hati ini. Bagaikan menjelaskan bahawa itulah yang sebenarnya. Yang sebaiknya untuk aku dan dia
“Boleh ke mereka terima saya?” ucapku penuh nada ragu-ragu.
“Pada awalnya mummy ada sikit rasa ragu-ragu. Tapi bila saya yakinkan dia, dia nampaknya setuju. Macam tadi, dia nampak teruja bila dapat jumpa Unie. Sampaikan masa nak balik tadi dia siap ajak Unie datang ke rumah untuk kenal semua ahli keluarga saya kan? Itu menunjukkan penerimaan dia terhadap Unie,”
Aku diam seketika. Terasa begitu tertekan saat ini. Ya Allah, sesungguhnya terlalu banyak rahsia yang aku ketahui dalam masa satu hari ini. Terlalu banyak sehinggakan tidak dapat aku terima semuanya dalam satu masa begini. Bantulah aku ya Allah. Aku buntu... buntu.
“Ayah awak?”
“Ayah tak pernah ada halangan. Dia hanya doakan kebahagiaan saya saja,”
Aku diam lagi. Lama. Dan dia hanya memandangaku dalam jarak waktu itu. Bingung aku jadinya. Dia? Sarah? Yang mana satu patut aku pilih? Sarah? Dia? Ah... aku mahukan kedua-duanya. Bisakah aku ya Allah... bisakah aku memilikku kedua-duanya?
“Saya tak nak desak Unie. Mungkin Unie perlukan masa. Fikirkanlah. Buat sembahyang Istikharah. Biar Allah tunjukkan apa yang lebih baik untuk Unie. Dan saya pun akan terus berdoa supaya saya akan jadi yang terbaik untuk Unie,”
Kata-kata itu membuatkan aku kembali menatap wajahnya. Suasana malap dari lampu di tempat parkir itu memberikan satu rasa syahdu di hati ini. Ya, sungguh aku juga cintakan dia. Semua yang ada pada dirinya. Bukan cinta biasa. Cinta yang lahir dari kesucian hati. Yang terbit dari keimanan yang dizahirkan dalam tingkah dan bicaranya. Namun layakkah aku? Layakkah aku menerima keajaiban ini? Dan bagaimana pula nanti dengan Sarah?
Lama kami bertatapan begitu. Berbicara tanpa suara. Bermadah rindu dalam diam. Menyulam cinta dalam kebisuan. Namun dalam kesuraman cahaya lampu itu, sedikitpun dia tidak mengambil kesempatan pada diri ini. Sedikitpun dia tidak menyentuhku, walaupun ada ketikanya aku dapat rasakan yang dia ingin sekali berbuat begitu. Dan aku, entah mengapa bagaikan terlalu percaya pada dirinya. Bagaikan terlalu yakin dengan keikhlasannya.
Ah .... Munirah, kau mahu menempah sengsara lagi ? Ingin kembali terjerumus dalam keadaan yang menyakitkan itu lagi? Ingin kembali mengalami kekecewaan itu lagi? Tidak serikkah engkau? Dulu kau sudah separuh mati dikecewakan. Hanya Allah sahaja yang memberikan kekuatan waktu itu. Dan kini kau mahu mengalaminya semula?
*************
Salam pada semua pembaca e novel ini,
merupakan bab terakhir di sini.... kalau tidak ada pelawaan dari penerbit, insyaallah akan di habiskan nanti di sini....
terima kasih keranan setia membaca. nantikan cerita yang lain pula ok?
salam sayang buat semua....
laila hanni
Comments: (19)
Comments: (12)
Bab 31
Setelah hampir setengah jam berlalu sejak azan Maghrib berkumandang dari corong radio di dalam MPV, Umar Rafiki masih duduk mendiamkan diri di pinggir bukit. Suasana senja sudah sedikit kelam, menunjukkan waktu solat Maghrib sudah semakin berlalu pergi. Aku yang tadinya sudah sedikit tenang, jadi resah kembali. Sampai bila dia mahu terus di sini. Kami ada hutang yang masih belum berbayar. Aku tidak mahu terlepas waktu solat kali ini.
Hairan rasa di hati. Tengahari dan petang tadi, dia kelihatan begitu menjaga solatnya. Seawal jam 12.45 tengahari dia sudah mempastikan kami semua sudah keluar dari syarikat penerbit yang pertama. Cepat-cepat dia mencadangkan supaya kami singgah dulu di masjid untuk sembahyang Zohor selepas makan tengahari. Begitu juga dengan Solat Asar. Tepat masuk waktunya, kami sudah berada di perkarangan masjid.
Dia memastikan kami tidak terlepas untuk turut sama berjemaah dengan imam, satu sikap yang aku rasakan begitu baik sekali. Kerana seseorang yang menjaga solat selalunya seorang yang bertanggungjawab dalam hidupnya. Waktu itu aku mula merasa kagum dengannya. Sudahlah orangnya kacak dan pekertinya mulia sekali. Dihiasi pula dengan sikap bertanggungjawab begitu. Dia seorang yang cukup sempurna di mataku. Namun mengapa hati ini bagaikan tidak sanggup menerimanya walaupun setiap tingkah dan kata-katanya sering mendamaikan hatiku? Mengapa masih ada ragu di hati ini dengan keikhlasannya? Benar-benarkah dia ikhlas? Ah....
Perlahan aku melangkah keluar dari MPVnya. Dengan hati yang penuh dengan debaran, aku menghampirinya. Aku berdiri di belakangnya yang masih diam di tempat dia mula-mula duduk tadi. Masih merajuk dengan kata-kataku tadi. Pastinya dia berkecil hati. Dalam marah, aku sendiri tidak tahu apa yang telah aku katakan kepadanya tadi.
“Awak.... waktu Maghrib dah dekat nak habis ni...,”
Diam.. Dia terus-terusan duduk sambil memeluk lututnya. Matanya terus merenung ke arah matahari yang sedang terbenam itu. Tidak ada sedikit pun reaksi darinya. Aku cuma mampu mamandang kepada belakang tubuhnya yang sedikit membongkok. Melihatkan otot-otot pejalnya yang terselindung di balik kemeja yang dipakainya hatiku jadi bergelodak kembali. Ah... dia ada segala-galanya. Dan aku? Apa yang aku ada? Cuma sekeping hati yang gersang. Layakkah untuk kami berganding bersama? Layakkah aku memenuhi apa yang diangan-angankan olehnya?
“Awak... kita kena solat ni...,” ulangku lagi setelah agak lama dia mendiamkan diri.
Diam lagi.
“Encik Um... em... Rafiki... berdosa kalau abaikan solat...,” untuk sekian kalinya aku merayu.
Dia berpaling kepadaku perlahan-lahan. Mata kami tertemu dan debar di hati ini jadi kian lega. Tiada lagi riak marah di situ. Aku menelan air liur sambil senyum padanya. Cukup aku rasa bersalah dengan sikapku yang kasar padanya petang tadi. Aku tidak sepatutnya mengatakan apa yang aku katakan tadi. Dia memandangku dengan wajah selamba.
“I thought you’re not going to ask,” katanya lembut. Tiada nada merajuk di situ. Lega sungguh rasa di hati.
Ah... sungguh lelaki ini mampu menggugat ketahanan dalam diri yang aku bina sejak Abang Izwan melukakan hatiku lama dulu. Sungguh aku terpikat kepadanya. Satu perasaan baru yang terasa begitu mendamaikan jiwa yang sering gundah selama ini. Yang tidak mampu untuk aku nafikan lagi. Dan... yang perlu aku buang jauh-jauh.... jika aku tidak mahu diri ini dikecewakan lagi.
Lama kami berpandangan.
“Janji dengan saya Unie tak jerit macam tadi lagi?” ucapnya kemudian.
Aku terpaku. Cuma mampu memberikan jawapan dengan kerdipan mataku untuk soalan itu.
“Janji yang Unie akan beri saya peluang untuk bersama Unie, rawat luka di hati Unie, jadi pendamping Unie?”
Aku menarik nafasku mendengarkan soalan itu. Hati masih ragu-ragu.
“Janji untuk beri saya peluang untuk bersama Unie, selesaikan masalah Unie tu?”
Mampukah aku berjanji dengannya? Bolehkah aku menerima huluran tangannya itu? Bisakah dia merawat hati yang telah parah dilukakan ini? Ya Allah, jika Kau kurniakan aku dengan lelaki sebaik ini, aku memohon agar nikmatMu ini Kau perluaskan lagi. Sesungguhnya Engkaulah yang memberikan segala nikmat untuk hambaMu. Aku memohon agar dia cukup baik untukku yang lemah ini. Cukup kuat untuk membimbing aku ke jalan yang Kau redhai. Cukup ikhlas untuk merawat kegersangan di hati ini. Aku tidak ingin dilukakan lagi ya Allah.
Akhirnya tanpa aku sedari, aku mengangguk perlahan. Dan dengan perlahan pula dia bangun sambil matanya terus merenung ke dalam mataku. Terus memaku aku di tempat aku berdiri. Mengkagumi rahmat tuhan yang ada di depan mataku ini.
Tubuh tegapnya disimbahi cahaya remang senja yang indah itu. Cahaya matahari yang kian jatuh itu menyuluh dari arah belakangnya membuatkan raut wajahnya kelihatan berbalam-balam di mataku. Menyembunyikan riak wajahnya dari pandangan mataku. Namun, tidak perlu lagi rasanya aku melihat reaksi wajah itu. Hatiku bagaikan terpanggil untuk menerima keikhlasan hatinya. Yang terlahir dari kata-kata dan perlakuannya selama ini.
“Janji lepas ni, Unie percayakan saya? Janji akan ikut saya ke mana saya akan bawa Unie? Tidak marah-marah macam tadi?”
Aku menarik nafas lagi? Perlukah aku berjanji? Dia senyum. Walaupun hambar sekali, dapat aku lihat keihklasan dalam senyuman itu.
“Jangan bimbang, saya tak akan bawa Unie ke tempat yang tak baik,”
Lama aku diam tanpa reaksi.
“Boleh?” dia bertanya separuh merayu.
Dan tanpa sedar aku mengangguk perlahan. Ada riak lega kelihatan di wajahnya.
“Jom… kita pergi solat,” katanya perlahan sekali.
Damai terasa di hati. Dia memandangku dengan sinar mata yang begitu meyakinkan. Bibirnya kembali tersenyum. Sambil melangkah ke MPVnya, hati kami berkata-kata sendiri. Aku menurut dengan seribu rasa yang tidak aku mengertikan. Permintaannya itu tadi terus terngiang di telinga.
****
Aku tidak pasti di mana kami berada. Tidak sampai pun lima minit, keretanya sudah berada di satu kawasan perumahan mewah. Ke mana dia ingin membawaku? Bukankah tadi dia mangajak aku bersolat? Tapi kenapa kami ke sini? Mungkinkah di celah-celah kawasan perumahan mewah ini ada sebuah masjid? Atau surau mungkin? Namun pertanyaan-pertanyaan itu hanya bergema di dalam mindaku sahaja. Masih tidak mampu untuk bersuara dek kerana debaran yang masih menggila di hati dengan apa yang berlaku pada kami tadi.
Akhirnya dia memberhentikan MPVnya di hadapan sebuah banglo besar yang tersergam indah. Dia menekan remote control dan perlahan-lahan pintu pagar rumah itu terbuka. Aku menarik nafas. Hatiku kembali berkocak. Rumah siapa?
“Rumah mummy saya,” bagaikan mengerti dengan kekeliruanku dia bersuara.
Aku menarik nafas panjang. Belum sempat aku berkata apa-apa, dia cepat-cepat bersuara.
“Tadi janji nak ikut saja ke mana saya bawa Unie kan?”
“Tapi, awak tak cakap nak bawa saya ke rumah emak awak?”
“Ini tempat sembahyang yang terdekat sekali yang saya boleh fikirkan setakat ini.
Waktu solat dah nak habis. Tadi kata tak nak terlepas waktu solat kan?” katanya yakin sambil menunjukkan jam di tangannya.
Kalaulah bukan kerana waktu Maghrib cuma tinggal kurang lebih limabelas minit sahaja lagi, pastinya aku sudah menunjukkan kedegilanku. Ingin sekali aku berdiam diri dalam kereta sehingga dia membawa aku ke tampat lain. Atau mungkin juga aku boleh terus pergi meninggalkan rumah ini. Mendapatkan teksi dan pergi ke mana-mana masjid terdekat. Namun, aku tidak mampu lakukan itu. Kawasan ini terlalu asing bagiku.
Badai di hati kembali melanda bila dia memberhentikan kertanya di bawah porch. Terletak di situ beberapa buah kereta mewah yang lain. Sebuah BMW yang aku tidak tahu siri yang entah ke berapa, sebuah Honda Accord dan sebuah Nissan Swift berwarna perak. Dan akhirnya kelihatan juga motosikal miliknya yang sering kali membuatkan hati ini berangan untuk membonceng bersamanya setiap kali aku terserempak dengan dia yang sedang menunggang. Dalam keadaan yang mendebarkan itu aku masih mampu untuk tersenyum sendiri bila mengingatkan betapa gatalnya aku mengangankan keadaan sebegitu.
“Kita dah sampai. Jom...,” katanya lembut.
Ah... mata itu, masih terus memainkan peranannya untuk terus-terusan mengocak ketenangan di jiwa. Badai di hati kian menggila apabila mengingatkan bahawa aku akan bertemu buat pertama kalinya dengan keluarganya. Terutama sekali dengan mummynya. Ah... Munirah, jangan perasan. Kamu hanya datang untuk tumpang sembahyang. Tidak lebih dari tu. Dan Umar Rafiki juga tidak pernah menggambarkan sesuatu yang lebih dari itu.
Ketibaan kami disambut oleh pembantu rumah yang membuka pintu apabila dia menekan loceng. Benar cakapnya itu, kehadiran kami ini tidak diketahui oleh ahli keluarganya. Dan di waktu-waktu begini pastinya masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Mandi dan bersembahyang. Maka tiada yang lain yang menyambut kehadiran kami ini.
“Eh... Rafiki? Dari mana ni?” tegur wanita berusia akhir tiga puluhan itu.
“Kak Odie ni... Nantilah kita cakap lepas ni. Kami belum solat lagi ni. Ini Cik Munirah. Dia pun nak solat. Akak bawa di ke bilik tamu ye?” pintanya dengan suara yang mesra juga.
“Ok ..., mari Cik Munirah, akak tunjukkan biliknya,”
Sambil memandang sekilas ke wajah Rafki, aku menurut langkah Kak Odie. Patutlah dia meminta aku memanggil dia dengan nama itu. Rupa-rupa itu panggilan ahli keluarganya. Dan, dia mahu aku memanggilnya begitu. Mengapa? Teringat aku pada kata-katanya tadi.
“Sebab Unie istimewa pada saya. Dan.... saya juga nak jadi seseorang yang istimewa untuk Unie,”
Ah... benarkah begitu? Setakat mana keistimewaanku pada dirinya? Cukup istimewa untuk diperkanalkan kepada ahli keluarganya? Meskipun perkenalan kami sendiri masih lagi setahun jagung usianya?
“Cik Munirah sembahyang kat sini. Kalau nak mandi, itu bilik airnya ye,” katanya sembil menunding kepada sebuah pintu yang bersebelahan dengan almari kayu jati yang tersergam indah di dalam bilik itu. Almari yang sarat dengan ukiran yang begitu halus sekali buatannya sungguh menarik perhatianku. Terdapat juga sebuah katil bersaiz king yang sama ukirannya dengan almari. Meja solek yang ada juga dibuat dengan ukiran yang sama. Suasana bilik tamu ini cukup mewah sekali. Kalaulah bilik tamunya sudah semewah ini, aku tidak mampu untuk bayangkan bagaimana mewahnya pula bilik tidur tuan empunya milik rumah ini.
“Kak Odie keluar dulu ye...,” katanya sambil berlalu pergi.
“Terima kasih kak,” jawabku sopan sambil mataku menyorot memandang dia yang berlalu pergi.
Tanpa membuang masa lagi aku cepat-cepat ke bilik mandi untuk mengangkat hadas kecil. Bila sahaja aku melangkah masuk ke bilik itu, aku terpana lagi. Bilik bersaiz kurang lebih 10 kaki x 10 kaki itu sekali lagi menunjukkan rekaan dalaman yang cukup menarik sekali. Ah... bilik mandinya pun cukup besar, sebesar bilik kedua di apartmen mulikku di Seri Kembangan. Kalaulah begini mewah rumahnya, apa perlu lagi lelaki ini berpindah ke rumah yang perlu disewanya? Bukankah menyusahkan tinggal sendirian begitu?
Aku cepat-cepat menunaikan solat Maghrib. Selesai sahaja solatku itu, kedengaran dari jauh suara azan tanda masuk waktu Isyak. Hatiku jadi sedikit tertanya-tanya. Bukankah tadi Rafiki mengatakan bahawa tiada masjid yang berdekatan dengan rumah ini. Bahawa rumah ini satu-satunya tempat sembahyang yang terdekat untuk kami bersolat. Aku jadi ragu-ragu.
Sebaik sahaja habis azan berkumandang aku berhajat untuk meneruskan solat Isyak. Tetapi tiba-tiba pintu bilik diketuk dan kemudian dikuak perlahan dari luar. Kepala Kak Odie terjenguk di situ. Dia sudah siap memakai telekung menunjukkan dia juga ingin bersolat.
“Cik Munirah, Rafiki ajak solat bersama dengan ahli keluarganya. Mari...,” ajaknya perlahan.
Aku agak terkejut dengan ajakkan itu jadi termanggu-manggu seketika.
“Marilah...,”
“A... iye...,”
Lantas aku bangun dengan teragak-agak. Solat berjemaah? Dengan keluarganya? Aku jadi kalut. Tidak mengerti apa yang sedang berlaku pada diriku di saat ini. Aku, berada di sini, di kalangan keluarganya dan akan bersolat jemaah bersama dia dan keluarganya. Sesuatu yang tidak pernah terlintas di kepalaku. Sesuatu yang terlalu peribadi aku rasakan. Layakkah aku? Layakkah aku...?
“Selalunya kalau dia balik awal dia pergi solat kat masjid dengan Pak Cik Safuan, ayah dia. Kalau dia tak sempat ke masjid memang kami sama-sama solat jemaah di rumah,” terang Kak Odie panjang lebar.
“Masjid dekat ke dengan rumah ni Kak Odie?”
“Dekat je... kat luar tu aje...berjalan kaki pun sampai. Cik Munirah tak perasan ke masa datang tadi?”
“A... em... tak perasan pulak...,”
Mana mungkin aku perasan jika waktu datang ke sini tadi aku dengan fikiran yang bercelaru. Tidak ada satu perkara pun yang aku nampak waktu itu. Sambil menurut langkahnya menuju ke tingkat atas, melilau mataku memerhatikan kemewahan rumah agam ini. Langsung tidak terbayangkan olehku akan berada di rumah yang begini mewah dan indah.
Kami tiba di hadapan pintu bilik yang terbuka luas. Aku melangkah perlahan. Terasa teragak-agak untuk masuk. Debaran di hati aku cuba redakan dengan menarik nafas panjang-panjang. Namun tidak sedikit pun debaran itu berkurangan. Lantas aku melangkah masuk. Bersedia untuk menghadapi keluarganya. Dan bersedia dengan pelbagai kemungkinan yang datang.
Aku disambut dengan senyuman yang cukup mesra oleh tiga wanita yang peringkat usianya berbeza. Yang pertama aku kira emaknya, berusia dalam lingkungan akhir lima puluhan atau awal enampuluhan. Yang kedua masih muda, mungkin lebih muda dariku. Dan yang ke tiga, lebih tua usianya, mungkin dalam lingkungan usia lapan puluhan. Itu mungkin neneknya.
Mereka bertiga sedang duduk dalam saf untuk berjemaah. Wanita yag lebih tua itu duduk di atas kerusi yang diletakkan di atas sejadah. Mungkin sudah terlalu uzur untuk solat sambil berdiri. Umar Rafiki tidak pula kelihatan di situ. Senyuman mereka kepada ku kelihatan begitu ikhlas sekali. Dan dalam ragu-ragu begitu, aku senyum kembali kepada mereka.
“Em... Cik Munirah... mari... kita solat sama-sama....,” tegur wanita yang paling muda itu. Siapakah dia? Hatiku terus tertanya-tanya.
Perlahan aku melangkah menghampirinya. Kami bersalaman buat pertama kalinya. Entah mengapa wajah itu bagaikan pernah aku lihat satu masa dulu. Tapi di mana?
“Em... ini rupanya Munirah... selama ni asyik duk dengar nama aje... hari ni baru dapat jumpa orangnya,”
Aku terpana mendengarkan kata-kata yang keluar dari bibir wanita yang aku rasakan emaknya. Aku lantas mengulurkan tanganku kepadanya sambil senyuman ragu-ragu terukir di bibir. Tidak pasti apa yang patut aku katakan. Debaran di hati makin kencang. Kami bersalaman seketika. Kemudian aku bersalaman pula dengan wanita yang lebih tua itu. Dia hanya tersenyum memandang ke wajahku tanpa sepatah kata.
“Em... puan... apa khabar?” tanyaku dengan ragu-ragu. Apa panggilan sebenar yang perlu aku gunakan untuknya? Datin? Puan Sri?
“Khabar baik... Sejuknya tangan Munirah...kenapa ni?”
“Emm... Tak ada apa-apa puan,”
“Eh... panggil makcik aje... tak payah panggil puan. Nak panggil mummy pun tak apa,”
Aku cuma senyum mendengarkan kata-katanya itu. Terasa malu dilayan sebaik itu.
“Maaflah ye tak sambut Munirah masa sampai tadi. Selalunya lepas sembahyang Isyak baru makcik turun ke bawah. Malaslah nak turun naik tangga tu. Tak larat nak turun naik. Bila dah selesai semua, barulah turun. Munirah dahaga ke? Belum minum kan?”
Pertanyaan demi pertanyaannya itu membuatkan aku tergamam lagi. Sungguh mesra orangnya. Senyumannya bagaikan senyuman seorang ibu yang sering meluahkan kasih sayang yang tidak bertepi kepada anaknya. Senyuman penuh ikhlas yang pernah satu ketika dulu aku pernah lihat di bibir ibuku sendiri. Tidak semana-mena sebakku datang bertandang lagi. Lantas aku berdehem, memperbetulkan suara ku.
“Tak apalah puan... ,”
“Kita solat dulu tak apa ye? Tunggu kejap lagi Rafiki datang, kita solat sama-sama. Lepas ayah Rafiki balik, kita makan malam ye?”
Aku mengangguk perlahan. Terasa damai memandang wajahnya.
Saat itu aku dapat rasakan seseorang melangkah masuk ke dalam bilik yang dikhaskan untuk bersolat itu. Aku tidak berpaling, tetapi aku bagaikan tahu siapa yang berada di belakangku itu. Aku bagaikan dapat merasakan panahan matanya menusuk jantungku walaupun dari belakang.
Ah, lelaki ini, kehadirannya dalam bilik ini bagaikan dapat aku rasakan biarpun aku tidak melihatnya. Aku menarik nafas panjang. Tidak sudah-sudah cuba melegakan debaran di dada yang bagaikan tidak mahu meninggalkan diri ini sejak pagi. Membuatkan aku kini bagaikan begitu letih sekali. Alangkah penatnya aku melayan rasa resah di hati begini.
“Semua dah siap rupanya,” suara riangnya itu menggambarkan perasaan hatinya.
Dan aku turut senyum bersama emaknya, neneknya dan gadis yng cukup menarik itu. Dan hati ini tidak putus-putus bertanya, siapa gerangan gadis ini? Apa hubungannya dengan Rafiki? Istimewakah dia pada lelaki ini?
“Unie, semuanya ok?”
Pertanyaan itu membuatkan aku berpaling perlahan kepadanya. Dia kini lengkap dengan baju melayu yang dipakai dengan sehelai kain pelikat. Di kepalanya terletak kemas sebiji kupiah putih. Dalam keadaan begitupun dia kelihatan begitu tampan sekali. Sungguh, hati ini sudah terpikat padanya.
“Unie...?”
Pertanyaan itu membuatkan aku tersentak dari lamunanku. Terasa malu apabila perilakuku itu disedarinya. Dia senyum tanda mengerti. Dan aku tidak lepas dari menyedari yang mummynya dan gadis itu juga turut tersenyum. Mungkin mereka juga tidak lepas dari menyedari perlakuan luar sedar ku sebentar tadi. Ah malunya.
“A... ya...ok. semuanya ok,” jawabku gugup.
Senyum di bibir itu terus mekar. Dan dengan nakal sekali dia mengenyitkan matanya kepadaku.
“Rafiki...?” sampuk mummynya menyedarkan kami yang sedang berbicara dengan isyarat mata, tanpa suara, namun penuh dengan makna. “Sembahyang dulu...,” meleret suaranya memberi nasihat.
Aku jadi malu dan hanya mendiamkan diri.
“Ha’ahlah, tak menyempat-nyempat. Solatlah dulu, baru main mata,” sampuk gadis itu.
Aku jadi bertambah malu bila perlakuan polos kami tadi ditegur. Alahai...
Rafiki ketawa riang sekali. Sungguh moodnya sudah kelihatan baik. Mudah sekali moodnya itu bertukar dari riang pada waktu paginya, menjadi marah dan merajuk pada waktu petangnya dan kini kembali riang semula.
‘Ok, jom kita solat,” katanya riang sambil mengambil tempat di hadapan sekali sebagai imam.
Lantas dia membaca bismillah dan mengucapkan dua kalimah shahadat. Dan sebagai satu-satunya lelaki yang ada hari ini dia melaungkan qamat sebagai tanda untuk memulakan solat. Gagah sekali kedengaran suaranya. Aku menghayati satu persatu kalimah dalam qamat yang dilaungkan itu. Rasa damai meresap ke hatiku.
Malam itu, buat pertama kalinya dia menjadi imamku dan aku menjadi makmumnya. Setiap bait bacaan surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek yang dibacanya menyuntik rasa damai dan tenang di hati. Aku menghayatinya satu persatu. Alunan suaranya yang membaca kedengaran begitu gagah sekali memandu kami makmum-makmumnya melaksanakan rukun islam yang kedua itu. Tidak… tidak pernah rasanya hatiku sedamai ini.
Setelah hampir setengah jam berlalu sejak azan Maghrib berkumandang dari corong radio di dalam MPV, Umar Rafiki masih duduk mendiamkan diri di pinggir bukit. Suasana senja sudah sedikit kelam, menunjukkan waktu solat Maghrib sudah semakin berlalu pergi. Aku yang tadinya sudah sedikit tenang, jadi resah kembali. Sampai bila dia mahu terus di sini. Kami ada hutang yang masih belum berbayar. Aku tidak mahu terlepas waktu solat kali ini.
Hairan rasa di hati. Tengahari dan petang tadi, dia kelihatan begitu menjaga solatnya. Seawal jam 12.45 tengahari dia sudah mempastikan kami semua sudah keluar dari syarikat penerbit yang pertama. Cepat-cepat dia mencadangkan supaya kami singgah dulu di masjid untuk sembahyang Zohor selepas makan tengahari. Begitu juga dengan Solat Asar. Tepat masuk waktunya, kami sudah berada di perkarangan masjid.
Dia memastikan kami tidak terlepas untuk turut sama berjemaah dengan imam, satu sikap yang aku rasakan begitu baik sekali. Kerana seseorang yang menjaga solat selalunya seorang yang bertanggungjawab dalam hidupnya. Waktu itu aku mula merasa kagum dengannya. Sudahlah orangnya kacak dan pekertinya mulia sekali. Dihiasi pula dengan sikap bertanggungjawab begitu. Dia seorang yang cukup sempurna di mataku. Namun mengapa hati ini bagaikan tidak sanggup menerimanya walaupun setiap tingkah dan kata-katanya sering mendamaikan hatiku? Mengapa masih ada ragu di hati ini dengan keikhlasannya? Benar-benarkah dia ikhlas? Ah....
Perlahan aku melangkah keluar dari MPVnya. Dengan hati yang penuh dengan debaran, aku menghampirinya. Aku berdiri di belakangnya yang masih diam di tempat dia mula-mula duduk tadi. Masih merajuk dengan kata-kataku tadi. Pastinya dia berkecil hati. Dalam marah, aku sendiri tidak tahu apa yang telah aku katakan kepadanya tadi.
“Awak.... waktu Maghrib dah dekat nak habis ni...,”
Diam.. Dia terus-terusan duduk sambil memeluk lututnya. Matanya terus merenung ke arah matahari yang sedang terbenam itu. Tidak ada sedikit pun reaksi darinya. Aku cuma mampu mamandang kepada belakang tubuhnya yang sedikit membongkok. Melihatkan otot-otot pejalnya yang terselindung di balik kemeja yang dipakainya hatiku jadi bergelodak kembali. Ah... dia ada segala-galanya. Dan aku? Apa yang aku ada? Cuma sekeping hati yang gersang. Layakkah untuk kami berganding bersama? Layakkah aku memenuhi apa yang diangan-angankan olehnya?
“Awak... kita kena solat ni...,” ulangku lagi setelah agak lama dia mendiamkan diri.
Diam lagi.
“Encik Um... em... Rafiki... berdosa kalau abaikan solat...,” untuk sekian kalinya aku merayu.
Dia berpaling kepadaku perlahan-lahan. Mata kami tertemu dan debar di hati ini jadi kian lega. Tiada lagi riak marah di situ. Aku menelan air liur sambil senyum padanya. Cukup aku rasa bersalah dengan sikapku yang kasar padanya petang tadi. Aku tidak sepatutnya mengatakan apa yang aku katakan tadi. Dia memandangku dengan wajah selamba.
“I thought you’re not going to ask,” katanya lembut. Tiada nada merajuk di situ. Lega sungguh rasa di hati.
Ah... sungguh lelaki ini mampu menggugat ketahanan dalam diri yang aku bina sejak Abang Izwan melukakan hatiku lama dulu. Sungguh aku terpikat kepadanya. Satu perasaan baru yang terasa begitu mendamaikan jiwa yang sering gundah selama ini. Yang tidak mampu untuk aku nafikan lagi. Dan... yang perlu aku buang jauh-jauh.... jika aku tidak mahu diri ini dikecewakan lagi.
Lama kami berpandangan.
“Janji dengan saya Unie tak jerit macam tadi lagi?” ucapnya kemudian.
Aku terpaku. Cuma mampu memberikan jawapan dengan kerdipan mataku untuk soalan itu.
“Janji yang Unie akan beri saya peluang untuk bersama Unie, rawat luka di hati Unie, jadi pendamping Unie?”
Aku menarik nafasku mendengarkan soalan itu. Hati masih ragu-ragu.
“Janji untuk beri saya peluang untuk bersama Unie, selesaikan masalah Unie tu?”
Mampukah aku berjanji dengannya? Bolehkah aku menerima huluran tangannya itu? Bisakah dia merawat hati yang telah parah dilukakan ini? Ya Allah, jika Kau kurniakan aku dengan lelaki sebaik ini, aku memohon agar nikmatMu ini Kau perluaskan lagi. Sesungguhnya Engkaulah yang memberikan segala nikmat untuk hambaMu. Aku memohon agar dia cukup baik untukku yang lemah ini. Cukup kuat untuk membimbing aku ke jalan yang Kau redhai. Cukup ikhlas untuk merawat kegersangan di hati ini. Aku tidak ingin dilukakan lagi ya Allah.
Akhirnya tanpa aku sedari, aku mengangguk perlahan. Dan dengan perlahan pula dia bangun sambil matanya terus merenung ke dalam mataku. Terus memaku aku di tempat aku berdiri. Mengkagumi rahmat tuhan yang ada di depan mataku ini.
Tubuh tegapnya disimbahi cahaya remang senja yang indah itu. Cahaya matahari yang kian jatuh itu menyuluh dari arah belakangnya membuatkan raut wajahnya kelihatan berbalam-balam di mataku. Menyembunyikan riak wajahnya dari pandangan mataku. Namun, tidak perlu lagi rasanya aku melihat reaksi wajah itu. Hatiku bagaikan terpanggil untuk menerima keikhlasan hatinya. Yang terlahir dari kata-kata dan perlakuannya selama ini.
“Janji lepas ni, Unie percayakan saya? Janji akan ikut saya ke mana saya akan bawa Unie? Tidak marah-marah macam tadi?”
Aku menarik nafas lagi? Perlukah aku berjanji? Dia senyum. Walaupun hambar sekali, dapat aku lihat keihklasan dalam senyuman itu.
“Jangan bimbang, saya tak akan bawa Unie ke tempat yang tak baik,”
Lama aku diam tanpa reaksi.
“Boleh?” dia bertanya separuh merayu.
Dan tanpa sedar aku mengangguk perlahan. Ada riak lega kelihatan di wajahnya.
“Jom… kita pergi solat,” katanya perlahan sekali.
Damai terasa di hati. Dia memandangku dengan sinar mata yang begitu meyakinkan. Bibirnya kembali tersenyum. Sambil melangkah ke MPVnya, hati kami berkata-kata sendiri. Aku menurut dengan seribu rasa yang tidak aku mengertikan. Permintaannya itu tadi terus terngiang di telinga.
****
Aku tidak pasti di mana kami berada. Tidak sampai pun lima minit, keretanya sudah berada di satu kawasan perumahan mewah. Ke mana dia ingin membawaku? Bukankah tadi dia mangajak aku bersolat? Tapi kenapa kami ke sini? Mungkinkah di celah-celah kawasan perumahan mewah ini ada sebuah masjid? Atau surau mungkin? Namun pertanyaan-pertanyaan itu hanya bergema di dalam mindaku sahaja. Masih tidak mampu untuk bersuara dek kerana debaran yang masih menggila di hati dengan apa yang berlaku pada kami tadi.
Akhirnya dia memberhentikan MPVnya di hadapan sebuah banglo besar yang tersergam indah. Dia menekan remote control dan perlahan-lahan pintu pagar rumah itu terbuka. Aku menarik nafas. Hatiku kembali berkocak. Rumah siapa?
“Rumah mummy saya,” bagaikan mengerti dengan kekeliruanku dia bersuara.
Aku menarik nafas panjang. Belum sempat aku berkata apa-apa, dia cepat-cepat bersuara.
“Tadi janji nak ikut saja ke mana saya bawa Unie kan?”
“Tapi, awak tak cakap nak bawa saya ke rumah emak awak?”
“Ini tempat sembahyang yang terdekat sekali yang saya boleh fikirkan setakat ini.
Waktu solat dah nak habis. Tadi kata tak nak terlepas waktu solat kan?” katanya yakin sambil menunjukkan jam di tangannya.
Kalaulah bukan kerana waktu Maghrib cuma tinggal kurang lebih limabelas minit sahaja lagi, pastinya aku sudah menunjukkan kedegilanku. Ingin sekali aku berdiam diri dalam kereta sehingga dia membawa aku ke tampat lain. Atau mungkin juga aku boleh terus pergi meninggalkan rumah ini. Mendapatkan teksi dan pergi ke mana-mana masjid terdekat. Namun, aku tidak mampu lakukan itu. Kawasan ini terlalu asing bagiku.
Badai di hati kembali melanda bila dia memberhentikan kertanya di bawah porch. Terletak di situ beberapa buah kereta mewah yang lain. Sebuah BMW yang aku tidak tahu siri yang entah ke berapa, sebuah Honda Accord dan sebuah Nissan Swift berwarna perak. Dan akhirnya kelihatan juga motosikal miliknya yang sering kali membuatkan hati ini berangan untuk membonceng bersamanya setiap kali aku terserempak dengan dia yang sedang menunggang. Dalam keadaan yang mendebarkan itu aku masih mampu untuk tersenyum sendiri bila mengingatkan betapa gatalnya aku mengangankan keadaan sebegitu.
“Kita dah sampai. Jom...,” katanya lembut.
Ah... mata itu, masih terus memainkan peranannya untuk terus-terusan mengocak ketenangan di jiwa. Badai di hati kian menggila apabila mengingatkan bahawa aku akan bertemu buat pertama kalinya dengan keluarganya. Terutama sekali dengan mummynya. Ah... Munirah, jangan perasan. Kamu hanya datang untuk tumpang sembahyang. Tidak lebih dari tu. Dan Umar Rafiki juga tidak pernah menggambarkan sesuatu yang lebih dari itu.
Ketibaan kami disambut oleh pembantu rumah yang membuka pintu apabila dia menekan loceng. Benar cakapnya itu, kehadiran kami ini tidak diketahui oleh ahli keluarganya. Dan di waktu-waktu begini pastinya masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Mandi dan bersembahyang. Maka tiada yang lain yang menyambut kehadiran kami ini.
“Eh... Rafiki? Dari mana ni?” tegur wanita berusia akhir tiga puluhan itu.
“Kak Odie ni... Nantilah kita cakap lepas ni. Kami belum solat lagi ni. Ini Cik Munirah. Dia pun nak solat. Akak bawa di ke bilik tamu ye?” pintanya dengan suara yang mesra juga.
“Ok ..., mari Cik Munirah, akak tunjukkan biliknya,”
Sambil memandang sekilas ke wajah Rafki, aku menurut langkah Kak Odie. Patutlah dia meminta aku memanggil dia dengan nama itu. Rupa-rupa itu panggilan ahli keluarganya. Dan, dia mahu aku memanggilnya begitu. Mengapa? Teringat aku pada kata-katanya tadi.
“Sebab Unie istimewa pada saya. Dan.... saya juga nak jadi seseorang yang istimewa untuk Unie,”
Ah... benarkah begitu? Setakat mana keistimewaanku pada dirinya? Cukup istimewa untuk diperkanalkan kepada ahli keluarganya? Meskipun perkenalan kami sendiri masih lagi setahun jagung usianya?
“Cik Munirah sembahyang kat sini. Kalau nak mandi, itu bilik airnya ye,” katanya sembil menunding kepada sebuah pintu yang bersebelahan dengan almari kayu jati yang tersergam indah di dalam bilik itu. Almari yang sarat dengan ukiran yang begitu halus sekali buatannya sungguh menarik perhatianku. Terdapat juga sebuah katil bersaiz king yang sama ukirannya dengan almari. Meja solek yang ada juga dibuat dengan ukiran yang sama. Suasana bilik tamu ini cukup mewah sekali. Kalaulah bilik tamunya sudah semewah ini, aku tidak mampu untuk bayangkan bagaimana mewahnya pula bilik tidur tuan empunya milik rumah ini.
“Kak Odie keluar dulu ye...,” katanya sambil berlalu pergi.
“Terima kasih kak,” jawabku sopan sambil mataku menyorot memandang dia yang berlalu pergi.
Tanpa membuang masa lagi aku cepat-cepat ke bilik mandi untuk mengangkat hadas kecil. Bila sahaja aku melangkah masuk ke bilik itu, aku terpana lagi. Bilik bersaiz kurang lebih 10 kaki x 10 kaki itu sekali lagi menunjukkan rekaan dalaman yang cukup menarik sekali. Ah... bilik mandinya pun cukup besar, sebesar bilik kedua di apartmen mulikku di Seri Kembangan. Kalaulah begini mewah rumahnya, apa perlu lagi lelaki ini berpindah ke rumah yang perlu disewanya? Bukankah menyusahkan tinggal sendirian begitu?
Aku cepat-cepat menunaikan solat Maghrib. Selesai sahaja solatku itu, kedengaran dari jauh suara azan tanda masuk waktu Isyak. Hatiku jadi sedikit tertanya-tanya. Bukankah tadi Rafiki mengatakan bahawa tiada masjid yang berdekatan dengan rumah ini. Bahawa rumah ini satu-satunya tempat sembahyang yang terdekat untuk kami bersolat. Aku jadi ragu-ragu.
Sebaik sahaja habis azan berkumandang aku berhajat untuk meneruskan solat Isyak. Tetapi tiba-tiba pintu bilik diketuk dan kemudian dikuak perlahan dari luar. Kepala Kak Odie terjenguk di situ. Dia sudah siap memakai telekung menunjukkan dia juga ingin bersolat.
“Cik Munirah, Rafiki ajak solat bersama dengan ahli keluarganya. Mari...,” ajaknya perlahan.
Aku agak terkejut dengan ajakkan itu jadi termanggu-manggu seketika.
“Marilah...,”
“A... iye...,”
Lantas aku bangun dengan teragak-agak. Solat berjemaah? Dengan keluarganya? Aku jadi kalut. Tidak mengerti apa yang sedang berlaku pada diriku di saat ini. Aku, berada di sini, di kalangan keluarganya dan akan bersolat jemaah bersama dia dan keluarganya. Sesuatu yang tidak pernah terlintas di kepalaku. Sesuatu yang terlalu peribadi aku rasakan. Layakkah aku? Layakkah aku...?
“Selalunya kalau dia balik awal dia pergi solat kat masjid dengan Pak Cik Safuan, ayah dia. Kalau dia tak sempat ke masjid memang kami sama-sama solat jemaah di rumah,” terang Kak Odie panjang lebar.
“Masjid dekat ke dengan rumah ni Kak Odie?”
“Dekat je... kat luar tu aje...berjalan kaki pun sampai. Cik Munirah tak perasan ke masa datang tadi?”
“A... em... tak perasan pulak...,”
Mana mungkin aku perasan jika waktu datang ke sini tadi aku dengan fikiran yang bercelaru. Tidak ada satu perkara pun yang aku nampak waktu itu. Sambil menurut langkahnya menuju ke tingkat atas, melilau mataku memerhatikan kemewahan rumah agam ini. Langsung tidak terbayangkan olehku akan berada di rumah yang begini mewah dan indah.
Kami tiba di hadapan pintu bilik yang terbuka luas. Aku melangkah perlahan. Terasa teragak-agak untuk masuk. Debaran di hati aku cuba redakan dengan menarik nafas panjang-panjang. Namun tidak sedikit pun debaran itu berkurangan. Lantas aku melangkah masuk. Bersedia untuk menghadapi keluarganya. Dan bersedia dengan pelbagai kemungkinan yang datang.
Aku disambut dengan senyuman yang cukup mesra oleh tiga wanita yang peringkat usianya berbeza. Yang pertama aku kira emaknya, berusia dalam lingkungan akhir lima puluhan atau awal enampuluhan. Yang kedua masih muda, mungkin lebih muda dariku. Dan yang ke tiga, lebih tua usianya, mungkin dalam lingkungan usia lapan puluhan. Itu mungkin neneknya.
Mereka bertiga sedang duduk dalam saf untuk berjemaah. Wanita yag lebih tua itu duduk di atas kerusi yang diletakkan di atas sejadah. Mungkin sudah terlalu uzur untuk solat sambil berdiri. Umar Rafiki tidak pula kelihatan di situ. Senyuman mereka kepada ku kelihatan begitu ikhlas sekali. Dan dalam ragu-ragu begitu, aku senyum kembali kepada mereka.
“Em... Cik Munirah... mari... kita solat sama-sama....,” tegur wanita yang paling muda itu. Siapakah dia? Hatiku terus tertanya-tanya.
Perlahan aku melangkah menghampirinya. Kami bersalaman buat pertama kalinya. Entah mengapa wajah itu bagaikan pernah aku lihat satu masa dulu. Tapi di mana?
“Em... ini rupanya Munirah... selama ni asyik duk dengar nama aje... hari ni baru dapat jumpa orangnya,”
Aku terpana mendengarkan kata-kata yang keluar dari bibir wanita yang aku rasakan emaknya. Aku lantas mengulurkan tanganku kepadanya sambil senyuman ragu-ragu terukir di bibir. Tidak pasti apa yang patut aku katakan. Debaran di hati makin kencang. Kami bersalaman seketika. Kemudian aku bersalaman pula dengan wanita yang lebih tua itu. Dia hanya tersenyum memandang ke wajahku tanpa sepatah kata.
“Em... puan... apa khabar?” tanyaku dengan ragu-ragu. Apa panggilan sebenar yang perlu aku gunakan untuknya? Datin? Puan Sri?
“Khabar baik... Sejuknya tangan Munirah...kenapa ni?”
“Emm... Tak ada apa-apa puan,”
“Eh... panggil makcik aje... tak payah panggil puan. Nak panggil mummy pun tak apa,”
Aku cuma senyum mendengarkan kata-katanya itu. Terasa malu dilayan sebaik itu.
“Maaflah ye tak sambut Munirah masa sampai tadi. Selalunya lepas sembahyang Isyak baru makcik turun ke bawah. Malaslah nak turun naik tangga tu. Tak larat nak turun naik. Bila dah selesai semua, barulah turun. Munirah dahaga ke? Belum minum kan?”
Pertanyaan demi pertanyaannya itu membuatkan aku tergamam lagi. Sungguh mesra orangnya. Senyumannya bagaikan senyuman seorang ibu yang sering meluahkan kasih sayang yang tidak bertepi kepada anaknya. Senyuman penuh ikhlas yang pernah satu ketika dulu aku pernah lihat di bibir ibuku sendiri. Tidak semana-mena sebakku datang bertandang lagi. Lantas aku berdehem, memperbetulkan suara ku.
“Tak apalah puan... ,”
“Kita solat dulu tak apa ye? Tunggu kejap lagi Rafiki datang, kita solat sama-sama. Lepas ayah Rafiki balik, kita makan malam ye?”
Aku mengangguk perlahan. Terasa damai memandang wajahnya.
Saat itu aku dapat rasakan seseorang melangkah masuk ke dalam bilik yang dikhaskan untuk bersolat itu. Aku tidak berpaling, tetapi aku bagaikan tahu siapa yang berada di belakangku itu. Aku bagaikan dapat merasakan panahan matanya menusuk jantungku walaupun dari belakang.
Ah, lelaki ini, kehadirannya dalam bilik ini bagaikan dapat aku rasakan biarpun aku tidak melihatnya. Aku menarik nafas panjang. Tidak sudah-sudah cuba melegakan debaran di dada yang bagaikan tidak mahu meninggalkan diri ini sejak pagi. Membuatkan aku kini bagaikan begitu letih sekali. Alangkah penatnya aku melayan rasa resah di hati begini.
“Semua dah siap rupanya,” suara riangnya itu menggambarkan perasaan hatinya.
Dan aku turut senyum bersama emaknya, neneknya dan gadis yng cukup menarik itu. Dan hati ini tidak putus-putus bertanya, siapa gerangan gadis ini? Apa hubungannya dengan Rafiki? Istimewakah dia pada lelaki ini?
“Unie, semuanya ok?”
Pertanyaan itu membuatkan aku berpaling perlahan kepadanya. Dia kini lengkap dengan baju melayu yang dipakai dengan sehelai kain pelikat. Di kepalanya terletak kemas sebiji kupiah putih. Dalam keadaan begitupun dia kelihatan begitu tampan sekali. Sungguh, hati ini sudah terpikat padanya.
“Unie...?”
Pertanyaan itu membuatkan aku tersentak dari lamunanku. Terasa malu apabila perilakuku itu disedarinya. Dia senyum tanda mengerti. Dan aku tidak lepas dari menyedari yang mummynya dan gadis itu juga turut tersenyum. Mungkin mereka juga tidak lepas dari menyedari perlakuan luar sedar ku sebentar tadi. Ah malunya.
“A... ya...ok. semuanya ok,” jawabku gugup.
Senyum di bibir itu terus mekar. Dan dengan nakal sekali dia mengenyitkan matanya kepadaku.
“Rafiki...?” sampuk mummynya menyedarkan kami yang sedang berbicara dengan isyarat mata, tanpa suara, namun penuh dengan makna. “Sembahyang dulu...,” meleret suaranya memberi nasihat.
Aku jadi malu dan hanya mendiamkan diri.
“Ha’ahlah, tak menyempat-nyempat. Solatlah dulu, baru main mata,” sampuk gadis itu.
Aku jadi bertambah malu bila perlakuan polos kami tadi ditegur. Alahai...
Rafiki ketawa riang sekali. Sungguh moodnya sudah kelihatan baik. Mudah sekali moodnya itu bertukar dari riang pada waktu paginya, menjadi marah dan merajuk pada waktu petangnya dan kini kembali riang semula.
‘Ok, jom kita solat,” katanya riang sambil mengambil tempat di hadapan sekali sebagai imam.
Lantas dia membaca bismillah dan mengucapkan dua kalimah shahadat. Dan sebagai satu-satunya lelaki yang ada hari ini dia melaungkan qamat sebagai tanda untuk memulakan solat. Gagah sekali kedengaran suaranya. Aku menghayati satu persatu kalimah dalam qamat yang dilaungkan itu. Rasa damai meresap ke hatiku.
Malam itu, buat pertama kalinya dia menjadi imamku dan aku menjadi makmumnya. Setiap bait bacaan surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek yang dibacanya menyuntik rasa damai dan tenang di hati. Aku menghayatinya satu persatu. Alunan suaranya yang membaca kedengaran begitu gagah sekali memandu kami makmum-makmumnya melaksanakan rukun islam yang kedua itu. Tidak… tidak pernah rasanya hatiku sedamai ini.
Comments: (7)
Jam di tangan menunjukkan ke pukul 2.00 petang apabila kami selesai membuat pemilihan buku di Syarikat McGraw Hill. Sepanjang waktu itu aku jadi tidak menentu. Serba-serbi yang aku lakukan seolah-olah seperti dalam mimpi. Terawang-awang rasanya dengan kata-katanya tadi. Bagaikan gadis remaja yang baru mengenal erti cinta, terasa begitu debarannya. Dan dia bagaikan mengerti perasaanku begitu memahami. Sering berada hampir denganku. Dan senyumnnya itu bagaikan terus membelai hatiku.
Sedaya mungkin aku menyembunyikan perasaanku ini dari terlalu polos. Aku tidak ingin dia atau mereka yang lain melihat aku terlalu teruja dengan perasaan ini. Malu rasanya bila dalam keadaan diriku ini ada yang tahu bahawa aku berangan-angan yang akan ada masa hadapan untuk aku dan dia. Kalaulah benar itu akan berlaku, biarlah Allah yang menentukannya. Biarlah mereka tahu dengan sendirinya. Bukan dari diriku yang bagaikan hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong.
Setelah kami melawati sebuah lagi syarikat penerbit di kawasan Shah Alam itu, kami pulang semula ke UPM. Selesai sudah lawatan kami untuk hari ini. Walaupun tidak banyak buku yang aku temui untuk pelajar-pelajar yang mengikuti kursus bagi jabatanku, puas rasanya hati ini. Esok masih ada satu hari lagi untuk kami habiskan lawatan kami ke syarikat penerbitan lain.
Aku sudah tidak pasti bagaimana akan aku lalui hari esok. Bersama dia di sisi menyebabkan aku bukan seperti diriku yang biasa. Aku yang biasanya tenang menghadapi kaum sejenisnya kini bertukar kepada seorang yang resah dan penuh debaran di hati bila bersamanya. Ingin sekali aku lari dari keadaan ini. Sungguh... sungguh aku tidak selesa dengan keadaan ini.
Selepas dia menghantar Kak Madihah ke tempat parkir berhadapan Perpustakaan Sultan Abdul Samad untuk mengambil keretanya untuk pulang, Umar Rafiki menghantar pula kami bertiga ke Fakulti Kejuruteraan untuk mengambil kereta masing-masing. Ketika aku mahu keluar dari MPVnya dia menahanku dari berbuat begitu. Tegak dia berdiri di pintu MPV berdekatan dengan tempat dudukku.
“Malam ni Unie ada hal ke? Nak ke mana-mana ke?”
Aku sepontan mengelengkan kepalaku bersama debar di hati. Mengapa? Apa tujuannya bertanya aku begitu.
“Tak...,”
“Saya hantar Unie balik. Kereta tinggalkan kat sini saja. Nanti kita beritahu pak guard supaya tengok-tengokkan kereta Unie tu,”
“Eh... tak payahlah.... saya balik sendiri,” cepat aku menjawab pelawaannya itu.
“Kenapa ni Unie, Umar?” tanya Kak Sufiah kehairanan. Jelas dia hairan mendengarkan aku yang separuh menjerit itu.
“Tak ada apa kak.. kami dah janji nak keluar kejap lagi. Jadi saya nak bawa dia balik. Tak payahlah dia drive kereta dia untuk balik. Sekarang pun dah pukul 6.00 ni. Terus aje keluar nanti. Lagipun esok saya boleh terus bawa dia ke sini dari kondo kami,” cepat lelaki di hadapanku ini menjawab.
Aku terlopong kehairanan mendengarkan kata-katanya itu. Sejak bila pula aku bersetuju keluar dengan dia? Bukankah tadi katanya dia mahu aku berfikir dahulu? Bukankah aku belum memberikan jawapan pada permintaannya tadi.
“Patutlah cakap bisik-bisik tadi... Emmm betul cakap Kak Madihah tadi rupanya. Unie dengan Umar ni memang ada apa-apa rupanya.... Kononnya nak sembunyikan ye...,” kata Kak Sufiah dengan gelak yang tidak langsung ditahannya.
Sungguh aku malu ketika itu. Sungguh aku tidak mampu untuk berkata-kata seketika.
“Tapi...,”
“Alah... betul kata Umar tu Unie, buat apa nak drive balik kalau ‘driver’ dah ada. Kalau akak, hari-haripun tak apa kalau ada yang datang ambil macam ni. Oklah both of you... have a very good time....,” katanya sambil berlalu pergi.
Ellen juga melangkah tanpa sebarang kata. Hanya senyuman tanda mengerti diberikan kepadaku. Dia mengangkat ibujarinya kepadaku. Aku cuba untuk memanggil mereka untuk menjelaskan keadaan sebenar. Ingin menyatakan bahawa aku sedikitpun tidak berjanji untuk keluar dengan dia. Bahawa semuanya ini hanya rancangan dia untuk memastikan aku tidak dapat melepaskan diri.
Setelah agak jauh mereka meninggalkan ku, aku berpaling kepadanya marah.
“Tengok apa yang awak dah buat?”
“Eh... apa yang saya dah buat,”
“Sekarang mereka dah fikir yang bukan-bukan pasal kita...,”
“Apa yang bukan-bukannya tu?” katanya sambil masih menduga perasaanku. “Unie takut mereka kata kita ada apa-apa hubungan?”
Aku diam. Dengan kedudukanku yang masih lagi duduk di kerusi penumpang MPVnya, mata kami berada pada paras yang setentang kini. Aku cuba sedaya mungkin untuk membalas pandanagannya itu. Cuba berlagak berani sedangkan dalam hati ini tuhan sahaja yang tahu betapa kuatnya debaran itu.
“Memang kita dah ada hubungan sekarang. Hubungan perasaan,” bisiknya perlahan untuk kata-kata yang terakhir itu.
Aku mengeluh kuat. Dengan perasaan yang bercelaru, mengalihkan pandangan. Untuk keluar dari MPVnya aku tidak mampu kerana dia masih menghalang perjalananku. Lantas aku bergerak ke pintu yang sebelah lagi. Cepat-cepat aku turun dan cuba menjauhkan diri. Namun dia lebih pantas memegang erat lenganku sebelum aku mampu meneruskan langkah.
Aku cuba menarik lenganku dari genggamannya. Aku tidak mahu dia menyentuhku walaupun beralaskan lengan bajuku. Aku takut sesuatu akan berlaku di hatiku jika dia terus berbuat begitu. Aku tidak akan membenarkan perasaan itu terus-terusan menebal di hatiku. Tidak....
“Unie, tadikan saya dah kata , we need to talk...,”
“There’s nothing to talk about,” ucapku marah. Masih cuba untuk melepaskan lenganku dari gengaman eratnya.
“There’s a lot of things that have to be cleared between us. Please Unie,”
“Saya tak faham Encik Umar...,”
“Rafiki...”
Aku buat tidak endah dengan kata-katanya itu. Ah ... apa perlunya aku memanggilnya dengan nama itu?
“Whatever...,” kataku sambil aku menarik lenganku yang masih lagi digenggam erat olehnya.
Dia melepaskan genggamannya. Matanya masih memandangku dengan senyuman di bibir. Mungkin dapat menelah apa yang ada di hatiku.
“Kita keluar...,”
“Saya tak nak keluar denagan awak,”
“Kenapa?”
“Kenapa pula saya mesti keluar dengan awak?,”
“Kan saya dah kata tadi... to make things clear between us,”
“Tak ada apa yang nak dijelaskan.,” jawabku pantas.
“Ho...ho...ho... banyak Unie, banyak...,” aku diam mendengarkan kata-katanya yang bersulam dengan tawa itu.
Aku memandang sekeliling kawasan parkir yang agak sunyi itu. Suasana petang Isnin itu agak damai kini. Pelajar-pelajar kebanyakkannya sudah pulang dari kuliah. Cuma sesekali kelihatan beberapa orang pelajar yang mungkin baru sahaja meninggalkan kawasan itu. Suasana yang sepi itu memberi ruang untuk aku dan dia berbicara dalam keadaan beremosi sebegitu.
“Ok... kita kira macam ni. Unie keluar dengan saya untuk malam ni dan malam esok, then apologise accepted,”
“Apologise? What do you mean?”
“Yang saya maksudkan tadi...,” katanya meleret. “Pertama, sebab Unie tuduh saya ambil meja Unie empat tahun lalu. Kedua, sebab Unie marah bila tahu yang saya dah masuk ke kondo yang Unie pun nakkan tu. Dan yang ke tiga, sebab Unie dah ambil sesuatu yang jadi kepunyaan saya selama ini,” katanya penuh keyakinan.
Kata-kata yang membawa rasa hairan di hatiku.
“Apa yang saya ambil dari awak?”
“Hati saya...,” bisiknya penuh romantis.
Tergamam aku dibuatnya mendengarkan kata-kata itu. Rasa marah yang ada di hati hilang begitu sahaja. Aku menarik nafas perlahan-lahan. Cuba menenangkan hati yang berkocak hebat. Aku tidak akan membiarkan dia dapat menelah apa yang aku rasakan ketika ini.
“Ok? Kita keluar untuk dua hari ini..? Dan nanti saya tidak akan menuntut Unie minta maaf dengan saya lagi,”
“Kenapa perlu sampai dua hari?” tanyaku perlahan.
Dia senyum lagi. Mungkin sedang merasakan yang aku sudah sedikit termakan dengan pelawaannya itu. Aku sendiri tidak mengerti perasaanku saat itu. Tipu kalau aku katakan yang aku tidak ingin keluar dengannya. Aku ingin bersamanya. Aku ingin sekali berbual dengannya. Mendengar apa yang ingin diperkatakannya. Seperti yang disebutnya tadi, ‘to make things clear between us.’
Tetapi aku tidak berani untuk menerima hakikat kata hatiku ini. Aku tidak sanggup nanti pertemuan pertama ini akan dijadikan alasan untuk dia terus mengharapkan pertemuan-pertamuan yang seterusnya. Aku masih belum rela ada apa-apa hubungan dengan mana-mana lelaki. Terutamanya dengan dia yang sering membawa seribu rasa debar di hati ini, resah di kalbu ini dan gundah di jiwa ini.
“Kerana ... pastinya ia tidak akan selesai dalam masa satu malam, kecuali kalau Unie nak postpone, bawa ke hujung minggu ini. Kita keluar satu hari, hari Ahad ni?” dia masih lagi memujukku.
Aku jadi keliru. Apa yang harus aku lakukan. Patutkah aku keluar dengannya dan semua ini selesai. Atau mungkinkah dia akan menuntut pertemuan demi pertemuan nanti? Apakah sebenarnya aku sendiri yang inginkan kami keluar bersama? Ah... buntu jadinya.
“Yang mana satu Unie pilih? Malam ni dan malam esok, atau hari Ahad nanti?”
“Ahad biasanya... saya ada hal lain...,” jawabku perlahan. Ingatanku kembali kepada Sarah.
“Pergi mengintai anak Unie?”
Kata-kata itu bagaakan menyentap jantungku dari tangkainya. Dari mana dia tahu aktiviti hari minggu ku itu?
“Mana awak tahu? Awak intai saya ke?” kataku dengan perasaan marah yang tiba-tiba terasa kembali meluap naik. Membakar hatiku, menyebabkan darahku bagaikan mengelegak tiba-tiba. Lantas membawa bahang di wajahku.
“Bila seseorang tu mula mengisi ruang kosong dalam hati kita, tak keterlaluan kan kalau kita nak tahu lebih lanjut tentang dia? Tambahan lagi kalau hidupnya tu penuh dengan misteri,”
Akukah yang dimaksudkan itu? Atau dia hanya berkata-kata untuk memancing aku untuk terus berbicara dengannya? Membuka ruang di hati ini untuk memudahkan dia terus membaca dan menelah apa yang tersirat di dalamnya?
“Saya tak suka di intai... diperhatikan...,” ucapku tegas. Cuba menerangkan kehendak hati ini.
“I can’t help it. You’re to intresting to be ignored,”
“Kenapa? Apa... yang ada pada saya?”
“Mysterious....,”
Dengan sepatah kata itu aku kembali menatap ke dalam matanya. Suasana petang yang makin redup itu sedikitpun tidak kami hiraukan lagi. Yang ada hanya aku dan dia. Bersatu dalam dunia kami yang penuh dengan tanda tanya. Mengapa? Mengapa dia mengambil berat pada diri ini? Mengapa dia mengatakan aku ini penuh dengan misteri?
Aku cuma seorang insan malang yang terpaksa menerima keadaan yang telah Allah tentukan untukku. Aku cuma insan lemah yang terpaksa akur dengan apa yang telah ditakdirkan untukku. Walaupun aku ingin lari dari keadaan itu, namun aku tidak punya kekuatan itu.
“So... macamana? Malam ni atau hari Ahad nanti?”
“Saya tak nak keluar dengan awak,” ulangku lagi dengan tegas.
“Berikan satu alasan kukuh untuk yakinkan saya yang Unie tak nak keluar dengan saya. Dari apa yang saya nampak, apa yang ada dalam hati Unie sebenarnya lain dari apa yang Unie ucapkan bukan? Unie kesunyiankan? Unie perlukan temankan? Unie...,”
“Tidak... tolong... tinggalkan saya sendirian. Tolong jangan ganggu saya... tolong biarkan saya sendirian,” jeritku.
Keadaan sekeliling tidak lagi aku endahkan. Aku sudah tidak menghiraukan lagi kalau perbualan kami ini menarik perhatian semua yang ada di situ. Aku mula melangkah lagi. Cuba untuk menjauhkan diri. Dalam keadaan kelam kabut itu itu aku terlupa di mana aku memarkirkan keretaku. Mataku melilau mencari di mana letaknya keretaku yang ku tinggalkan di situ sejak pagi tadi.
Namun langkahku terhenti lagi bila dia tiba-tiba telah berada di hadapanku. Menghalang aku dari terus melangkah. Tubuh kami hampir melanggar satu sama lain. Menyebabkan aku terjerit sekali lagi akibat terkejut.
“Jangan lari dari hakikat sebenar Unie. Unie tak boleh terus macam ni. Tak baik kalau terus macam ni. Unie kena kuat menghadapinya. Dan kalau Unie perlukan teman, biarlah saya jadi teman Unie. Saya nak temankan Unie, nak dampingi Unie hadapi semua ini, nak barikan kekuatan untuk Unie berhadapan dengan keadaan ini. Jangan lari dari keadaan Unie, hadapinya kalau Unie nak hak Unie terbela. Dan... saya sanggup bersama Unie,”
Entah mengapa kata-kata itu membawa sebak di hati ini. Airmataku tidak mampu untuk aku bendung. Dia tahu tentang diriku. Setakat mana dia tahu? Siapa yang memberitahunya? Kak Pah ? Suzana? Siapa lagi kalau bukan mereka.
Dalam kekalutan itu, sebuah motosikal menghampiri kami. Membuatkan bicara kami yang hangat tadi, terhenti seketika.
“Kenapa ni cik.... apa hal ni? Encik ni ganggu cik ke?” tanya pengawal keselamatan itu dengan penuh hairan.
Aku memandang wajah lelaki separuh umur itu dengan linangan airmata yang tidak mampu untuk aku hentikan. Mulutku tidak mampu untuk berkata apa-apa.
“Tak apa encik, ni... isteri saya. Kami... ada masalah sikit,” cepat Umar Rafiki berkata.
Aku jadi terpana. Memandang wajahnya dengan cukup terperanjat. Mengapa dia berkata begitu?
“Oh... maaf lah encik? Tak apalah... saya tak nak ganggu. Encik kena selasaikan baik-baik ni. Saya pergi dulu.... selesaikan ye encik. Tak baik gaduh-gaduh kat sini. Nanti semua orang tahu,” katanya.
“Tak apa... salah faham sikit aje. Kami dah ok ni...,” ucap Umar Rafiki dengan yakin sekali. Aku mengelengkan kepala. Masih terkejut dengan semua yang berlaku ini.
“Baliklah cik... selesaikan kat rumah. Hal rumah tangga ni jangan dedahkan pada orang. Jatuh maruah kita...,” katanya khas untukku. Mungkin di sini dia merasakan aku yang bersalah. Mungkin baginya Umar Rafiki yang betul. Ah... aku sendiri sudah jadi keliru. Melihatkan aku diam dia menyambung kata sambil berlalu pergi, “saya pergi dulu ye,”.
Aku jadi gamam dengan keadaan itu. Setelah pegawai keselamatan itu pergi aku mengalih pandanganku kepada Umar Rafiki. Cukup aku marah saat itu. Terasa terpukul dengan sikapnya yang begitu mudah mengambil kesempatan dalam keadaanku yang sedang menangis hiba begini.
“Apa yang awak buat ni ha? Apa yang awak nak sebenarnya?” jeritku marah.
“Unie, please... jangan tarik perhatian orang kat sini. Malu... kita pergi satu tempat... bincang baik-baik ok?”
“Siapa awak... siapa awak... yang nak ambil tahu hal saya?” kataku dengan nada yang masih marah.
Sungguh aku marah saat itu kerana sikapnya yang begitu menjaga tepi kain itu. Wajahnya kelihatan sedikit terkejut dengan reaksiku itu. Pantas dia menarik lenganku untuk kembali ke MPVnya. Dan tanpa daya, aku terpaksa mengikut langkahnya. Terpaksa berlari anak kerana lenganku masih dalam genggamannya. Terpaksa menyamakan langkahku dengan langkahnya yang panjang itu. Akhirnya tercungap-cungap aku bila kami tiba di MPVnya. Sesak dadaku akibat terkejut dengan tindakannya. Dia menolak aku masuk ke dalam MPV sehinggakan aku terduduk di kerusi penumpang sebelah pemandu.
“Jangan keluar...,” katanya dengan nada suara yang tegas sekali.
Matanya tajam menggambarkan kemarahan yang amat sangat. Cuma wajahnya sahaja yang kelihatan tenang. Namun ketajaman suara dan riak matanya membuatkan terasa kecut perutku. Saat itu aku dapat merasakan kemarahan yang aku rasakan sebentar tadi melayang, bertukar pula dengan rasa takut.
Aku tidak pernah tahu yang dia punya sikap sebegini. Entah mengapa, kenangan empat tahun lalu ketika matanya tajam memandang padaku saat marahnya meluap-luap, kembali menerpa ke dalam ingatan. Bagaikan tergambar di layar perak, tajam renungannya yang menggambarkan kemarahannya itu. Membuatkan aku terpaku di tempat dudukku.
Dia mengambil tempatnya di ruang pemandu. Sepanjang waktu itu matanya tajam merenung ke dalam mataku. Membuatkan aku, untuk seketika waktu tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Hanya merenung kembali ke dalam matanya.
Sepanjang waktu dia memandu, aku tidak berani untuk berpaling kepadanya. Mataku hanya liar memandang ke luar tingkap. Namun, tidak satu pun pemandangan di luar kenderaan itu masuk ke dalam ingatanku. Semuanya jadi kabur, sehinggakan bila dia memberhentikan MPVnya itu aku sendiri tidak tahu di mana kami berada. Yang aku tahu cuma kini kami berada di pinggir sebuah bukit yang menghadap ke kawasan tanah lapang yang cukup indah dan mendamaikan.
Dia turun dari kenderaannya itu. Lama aku diam di tempat dudukku. Hanya memerhatikannya yang sedang duduk di pinggir bukit itu. Matanya terus merenung jauh ke arah matahari yang sudah mula tenggelam di ufuk barat. Warna jingga mula meliputi langit menunjukkan waktu maghrib sudah masuk.
Waktu itu aku sendiri sudah tidak mampu untuk berfikir lagi. Marahku tadi sudah pergi menjauh. Cuma rasa resah yang memenuhi ruang hatiku saat itu. Apakah dia akan terus di situ? Dan aku terus di sini? Melayan resah masing-masing?
Popular Posts
-
Bab 28 “Mai…. Bangun… dah dekat subuh…,” Lembut sekali suara itu mengejutkan dia dari tidurnya. Membawa senyum ke bibirnya dalam ...
-
Bab 10 “Mmmm ..... Macam mana saya nak mulakan ye?” “Apa yang kau nak cakap tadi...cakaplah...,” Mai diam sambil matanya memandan...
-
"Aku ingin menjadi cinta terakhirmu, meskipun aku bukan cinta pertamamu...." ~~~ Dia memandangku sambil menghela naf...
-
Bab 30 “Nabil..., mana umi?” “Kat tepi pantai..,” “Eh, buat apa kat sana? Kan hujan ni... angin pun kuat tu...,”...
-
Bab 29 Kereta Mai perlahan-perlahan berhenti di tepi jalan berhampiran warung tempat Syamsul berniaga. Syamsul mengerling ke ar...
-
Pertemuan pertama Idayu dan Hairi, membuahkan rasa cinta di hati Hairi terhadap gadis pingitan ini. Walaupun dirinya sukar ...
-
Bab 31 Tiada saat yang lebih indah selain dari saat diri dicintai dan mencintai. Tidak pernah dia tahu akan ujudnya perasaan...
-
Bab 33 “Abang rasa abang kena cari dua tiga orang pekerja la Mai. Susah nak uruskan warung tu seorang-seorang bila dah buka sa...
-
BAB 27 Ya Allah ya tuhanku, jika perasaan ini salah, mengapa Kau hadirkan ia di hatiku? Jika aku berdosa kerana merasakan sebegini, mengap...